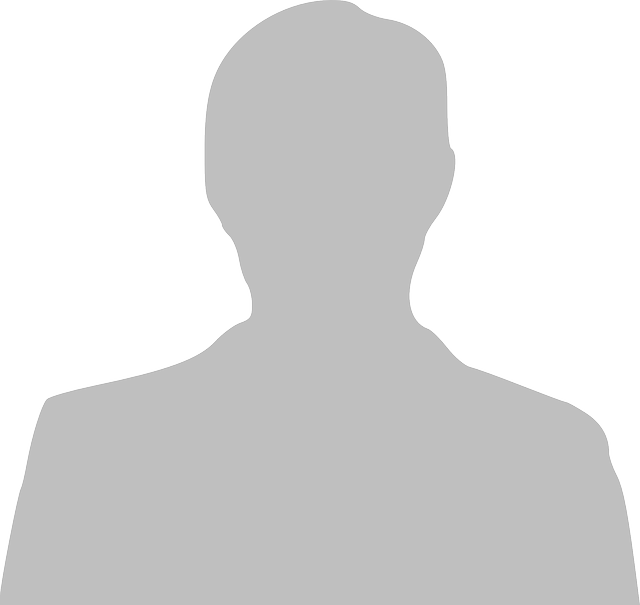Menduga Asal Usul ‘Peti Tua Bermotif Indah’ yang ‘Terdampar’ di Kampung Malawake, Dhawe
redaksi - Rabu, 12 November 2025 17:33 Peti berukir Sisik Ikan yang tersimpan di rumah Bapak Sebastianus Suara (68) di Kampung Malawake, Kelurahan Dhawe, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. (sumber: Maxi ali)
Peti berukir Sisik Ikan yang tersimpan di rumah Bapak Sebastianus Suara (68) di Kampung Malawake, Kelurahan Dhawe, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. (sumber: Maxi ali)JUMAT, 30 Juni 2023 lalu, sekitar pukul 10.30 Wita, saya dan kerabatku, Rikcy dari Lambo, bertolak dari penginapan S@antalum, Danga menuju Dhawe.
Kami bermaksud menemui para ibu pengrajin tenun Ragi Mbay di Kelurahan Dhawe, Kecamatan Aesesa, sebagaimana ada dalam daftar yang disediakan Diskoperindang Kabupaten Nagekeo.
Oleh karena belum pernah menyambangi Dhawe, kami pun mengandalkan Google Maps. ‘Mbah Google’ mengatakan jarak S@ntalum ke Dhawae, 5,8 km, dan dapat ditempuh dalam tempo 11 menit.
Namun, di tengah perjalanan, semenjak berbelok ke kanan dari jalan ‘Jalur Tengah Mbay-Boawae’ di wilayah Nggolo Mbay, sinyal handphone ‘menghilang’ .
Kami kemudian mengandalkan kebaikan hati orang-orang yang kami jumpai yang kebetulan ada di pinggir jalan.
Gagal Mencapai Kampung Adat Dhawe
Di depan SDI Rata, kami bertemu dua remaja putri yang berdiri di pintu pagar, baru keluar dari rumah kerabat mereka. Kepada mereka kami menanyakan alamat rumah wanita penenun yang mereka kenal.
Oleh kedua remaja putri itu, kami di arahkan ke rumah Mama Lina.
“Mama Lina itu salah satu wanita penenun senior di sini,” kata salah satu dari keduannya.
‘Tapi om harus berbalik arah. Tidak terlalu jauh dari sini, rumahnya ada di sebelah kanan, rumah kolong” sambung remaja putri yang pertama, yang bertubuh tinggi dan langsing.
‘Lalu, di mana letak kampung adat Dhawe?”, kami bertanya lagi.
“Itu ada jauh di atas bukit. Jalan masuknya tak jauh dari rumah Mama Lina,” jawab remaja putri lainnya yang tampak lebih pendek dan agak gemuk.
Ricky pun mengemudikan sepeda motor berbalik ke arah yang ditunjuk oleh dua remaja putri baik hati itu.
Namun, ketika sudah di depan halaman rumah Mama Lina, Ricky menyarankan untuk langsung ke Kampung Adat Dhawe.
“Kita foto-foto dulu di sana (kampung adat Dhawe), Abang,” katanya. Saya pun mengangguk, setuju.
Jalan masuk ke kampung yang menjadi salah satu destinasi wisata budaya Nagekeo itu, tak ada penanda. Artinya, tak ada papan nama dan petunjuk arah sama sekali.
Dalam hati, saya bergunam: “Sepertinya destinasi wisata budaya Kampung Adat Dhawe masih dibiarkan eksis secara natural. Wisawatan harus berjibaku kalau ingin berkunjung ke sana. Tapi seberapa besar daya pikat Kampung Adat Dhawe untuk menarik wisatawan?”
Walau tak ada penunjuk arah ke sana, kami percaya 100 persen pada keterangan dua remaja putri tadi.
Jalan menuju kampung legendaris itu sempit dan menanjak. Pada 500 meter pertama, kondisi jalan cukup bagus. Artinya, aspalnya masih tampak kuat melekat di tanah.
Selanjutnya, tampak makin banyak bongkahan batu bertebaran di jalan. Kami terus menanjak pelan, bak seekor kura-kura yang sedang menapaki pantai berpasir tebal menuju sarang untuk meletakkan butir-butir telurnya.
Kemudian kami tiba di satu tanjakan yang cukup tajam. ‘Kuda besi’ yang dikendalikan Ricky tiba-tiba ‘menyerah’, mesinnya mati.
Ia melorot mundur. Ricky berusaha menahan, tapi ‘barang bodoh’ iru terus saja bergerak mundur.
Melihat Ricky semakin tak berdaya menahan gerak mudur ‘kuda besi’ itu, saya pun meloncat.
Tetapi, karena kondisi jalanan yang miring sekitar 60 derajad, dan penuh dengan batu-batu terlepas, saya kehilangan tumpuan.
Saya pun terbuang ke belakang dalam posisi telentang. Sementara itu Ricky masih berjuang keras menahan ‘kuda’nya. Tapi, akhirnya dia pun tak berdaya, lalu terjatuh bersama ‘kuda’nya itu.
Waktu itu kami baru menyadari bahwa jalanan itu tak pantas dilintasi oleh pesepeda motor.
Ricky bangkit, wajahnya pucat pasi. Tapi, dia rupanya lebih mengkuatirkan keadaan saya.
“Bagaiamana, Abang?” dia bertanya.
‘Tidak apa-apa,” jawabku singkat.
‘Tapi Abang, saya kuatir karena saya lihat Abang terbuang beberapa meter ke belakang,” katanya lagi.
Meski begitu, saya memang merasa baik-baik saja. Hanya, bagian pantat yang terasa agak perih, terbentur pada bongkahan batu. Punggung aman, karena ada tas rangsel cukup tebal mengganjal di belakang.
Setelah itu, spontan kami berdua ‘balik kanan’, tanpa banyak bicara. Niat untuk berfoto-foto, di Kampung Adat Dhawe, buyar, menguap bak asap diterjang angin keras.
Kami pun segera menuju ke rumah Mama Lina. Ternyata, pintu rumahnya tertutup. Mama Lina rupanya sedang pergi.
Melihat kami memasuki halaman rumah Mama Lina, saudara Mama Lina yang rumahnya bersebelahan, mengajak kami masuk ke rumahnya.
Ketika kami menceritakan pengalaman ‘terjatuh’ dari ‘kuda tunggangan’, ibu separuh baya itu spontan menjawab: “Aduh, kalau kami tahu bahwa Pak mau ke sana, kami pasti melarang.”
"Soalnya, jalannya jelek sekali. Sudah banyak yang jatuh dari sepeda motor di tanjakan itu,” ujarnya lagi dengan wajah prihatin.
Kedua remaja putri yang kami jumpai tadi ternyata anak dari ibu itu, kerabat dekat Mama Lina.
Setelah itu, ia menyuruh salah satu remaja itu, pergi memanggil Mama Lina dan suaminya yang sedang bekerja di kebun di pinggir sungai, di belakang rumah mereka.
Tak lama kemudian, seorang bapak yang berkumis lebat dan sudah beruban, tiba. Ia langsung mengajak kami masuk ke rumahnya.
Kemudian kami bertiga duduk bersila di atas bale-bale bambu. Legah, dan teduh, walau di luar rumah sinar mentari sangat terik.
Kemudian bapak berkumis lebat itu memperkenalkan, ‘Istri saya bernama Lina. Dia seorang penenun, hanya belakangan ini sudah susah melakukan kegiatan itu, karena matanya mulai rabun’
‘Oh, mama Paulina ya’, sambung Ricky.
“ Bukan Paulina, tetapi Marselina,” ujarnya dengan nada meyakinkan.
“Saya sendiri bernama Sebastianus Suara.” Kemudian ia segera menyambung: ‘Ya, jangan heran pak, nama saya begitu. Karena saya dilahirkan pada Hari Pemungutan Suara (Pemilu I) tahun 1955,” ujarnya, sembari tersenyum.
Awal Mula Suku Dhawe
Dari mulut Sebastianus Suara, pria yang murah senyum itu, kami mendengar banyak kisah mengenai Dhawe.
Bahkan, untuk memudahkan kami mengikuti narasinya, ia memperlihatkan sebuah buku --atau lebih pas disebut ‘manuskrip’ karena belum diterbitkan—berjudul “Sejarah Suku Dhawe.”
Manuskrip itu memuat narasi yang cukup detil mengenai Suku Dhawe.
Sebetulnya, narasi sekilas mengenai nenek moyang orang Dhawe pernah ditulis oleh Hamilton, R.W. Dalam tulisannya itu Hamilton mengatakan bahwa pribumi Dhawe pernah mengalami kontak dengan para pelaut dan pedagang dari Goa (Gowa) dan juga Bima.
Hamilton mencatat bahwa setelah berlabuh di pantai utara Flores dan tinggal beberapa lama di wilayah orang Dhawe di datatan Mbay, Keraeng Jogo kemudian menjodohkan putrinya Supi dan Tuju Bae, seorang pria dari suku asli Dhawe.
Tuju Bae kemudian masuk Islam dan mengambil nama Abdulah Tuju. Dari situlah asal mula Komunitas Adat Mbay.
Menurut Hamilton salah satu jejak paling nyata dari perjumpaan itu adalah tradisi seni tenun songket: Lipa Dhowik.
Narasi asal usul Suku Dhawe dicatat oleh Maria Parni Pora, Irawan Setyabudi, Rizki Alfian, para peneliti Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang . Catatan yang dibuat berdasarkan penuturan tetua adat Mus Jera itu dipublikasikan pada 2022 di Jurnal LOCAL WISDOM, 14(1): 1-17.
Menurut Mus Jera, kisah asal-usul Kampung Adat Dhawe (Ola Dhawe) berawal dari dua saudara yatim piatu bernama Dhawe dan Dhengi. Dhawe adalah sang kakak laki-laki, sementara Dhengi adalah adik perempuannya.
Mereka hidup bersama penduduk kampung dan menggantungkan hidup dari ladang jagung yang letaknya cukup jauh dari permukiman.
Suatu ketika, saat jagung mulai mengering dan siap dipanen, sekawanan babi datang merusak ladang mereka. Melihat hal itu, Dhawe memerintahkan anjing kesayangannya, Ebo Rua, untuk mengusir kawanan babi. Ebo Rua kemudian mengejar seekor induk babi hingga ke dalam gua—tempat sarang babi tersebut.
Namun, saat tiba di gua, Dhawe terkejut melihat anjingnya dan induk babi itu berbicara satu sama lain. Mereka membicarakan cara bertahan hidup selama tujuh hari ke depan.
Dalam percakapan itu, sang babi menyampaikan pesan dari Ga’e Bapu, Tuhan Semesta Alam, bahwa Ia murka kepada manusia karena telah melanggar janji dan sumpah mereka.
Ga’e Bapu akan menjatuhkan dua hukuman besar: pertama, tidak akan turun hujan, dan kedua, laut akan naik menutupi seluruh daratan.
Mendengar hal itu, Dhawe dan Dhengi segera bersiap. Dalam waktu tujuh hari, mereka membangun sebuah perahu besar dan menyiapkan bekal berupa enam genggam tanah, enam genggam abu dapur, dan enam genggam arang.
Pada hari keenam, perahu itu selesai dibangun. Langit mulai gerimis, angin kencang bertiup, dan pada hari ketujuh, air laut benar-benar naik menenggelamkan bumi.
Keduanya segera masuk ke dalam perahu bersama seluruh bekal yang telah disiapkan. Setelah menerima petunjuk dari Ga’e Bapu, Dhawe mengambil tanah, abu dapur, dan arang itu, lalu menyebarkannya ke arah matahari terbit dan matahari terbenam.
Tak lama kemudian, air laut mulai surut. Tanah yang ditebarkan berubah menjadi tanah subur, abu dapur menjadi pasir, dan arang berubah menjadi batu.
Perahu besar mereka akhirnya terdampar di sebuah tempat yang kemudian disebut Ola Dhawe — Ola berarti kampung, dan Dhawe diambil dari nama sang kakak. Rumah besar yang mereka tinggali disebut Kowa Dhawe, artinya perahu besar, dan hingga kini nama itu masih dikenal oleh masyarakat setempat.
Untuk melanjutkan keturunan, Dhawe menikahidengan saudari kandungnya, Dhengi, dan dari perkawinan itu lahirlah empat pasang anak kembar, yang menjadi leluhur pertama masyarakat Dhawe
Merujuk ke manuskrip ‘Sejarah Suku Dhawe’, Sebastianus Suara menerangkan bahwa pasangan Dhawe-Dhengi melahirkan empat pasangan anak kembar yaitu: pasangan kembar pertama: Togo–Mogo, Mogo (laki-laki) dan Togo (perempuan); kedua, Te–Jere: Te (laki-laki) dan Jere (perempuan); ketiga, Dhae–Tey: Dhae (laki-laki) dan Tey (perempuan) dan pasangan kembar keempat, Bale–Be’o: Bale (laki-laki) dan Be’o (perempuan).
Setelah anak-anak mereka dewasa, Dhawe dan Dhengi berpesan kepada anak-anak mereka, Togo -Mogo, untuk tinggal di Desa Ola Dhawe di rumah yang telah mereka bangun, yaitu di Kowa Dhawe. Togo dan Mogo membangun sebuah rumah lain dan menamainya "Dhengi Dhawe".
Sementara itu, Dhawe - Dhengi, bersama ketiga pasangan anak kembar lainnya pergi mencari tanah baru sembari membawa sisa tanah lima genggam.
Togo - Mogo memiliki seorang putri bernama "Tawa". Tawa menikah dengan seorang pelaut asing dari Goa (Gowa) bernama "Ana Kodha Goru" (Ana Kodha = Kapten).
Ana Kodha Goru kemudian menetap di Ola Dhawe dan ditugaskan sebagai pemimpin perang dalam menjaga keamanan di laut dan darat (Mosa Sike, Laki Bani).
Pasangan Ana Kodha Goru dan Tawa memiliki anak bernama "Wegu" dan "Tadi". Setelah dewasa Tadi menikah dan membangun rumah tangga. Ia dan keluarga barunya hidup terpisah dari orang tuannya. Tetapi, Wegu masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya.
Kemudian, setelah Ana Kodha Goru dan Tawa, meninggal dunia, Wegu menjadi yatim piatu. Masyarakat Ola Dhawe memberinya julukan "Wegu Ana Ralo" (Wegu si yatim piatu).
Kemudian Wegu menikan dan menetap di Ola Dhawe bersama istrinya. Wegu kemudian mengajak para "Mosalaki" (tetua) Ola Dhawe bermusyawarah untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat kawanan kerbau yang lewat. Mereka juga bersepakat melakukan "Pogo Peo, Mula Peo, dan Para Peo" (menebang Peo, menanam Peo, dan meresmikan Peo).
Selain membahas soal Peo, Wegu dan Mosalaki dari Ola Dhawe juga membahas ajaran dan tata cata penyelenggaraan pesta adat Zebu Kobe (Kenduri).
Zebu Kobe adalah upacara malam penutupan jenazah agar arwah orang yang meninggal meraih Lau Nitu Wura (kehidupan bahagia di akhirat). Acara ini juga dimeriahkan dengan 'Teke Dhegha' (Tarian Tandak).
Mereka juga membicarakan tata upacara adat Tau Nuwa (Sunatan) - upacara pendewasaan bagi remaja laki-laki, dan upacara Zaba Ngi'i (Potong Gigi) -upacara pendewasaan remaja perempuan
Kampung Ola Dhawe sendiri terletak di atas punggung bukit, dikelilingi jurang, sehingga menyulitkan musuh untuk menyerangnya. Kampung itu membujur dari Ulu Ola Dhawe hingga Eko Dhoa Kata.
Penduduk Ola Dhawe terdiri dari lima keluarga besar yang mendiami lima rumah adat. Mereka adalah keturunan Dhawe-Dhengi dan empat pasangan anak kembar mereka.
Para penghuni kelima rumah adat tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk menjaga keutuhan Ola Dhawe.
Pada masa ini, Suku Dhawe tidak lagi bermukim di Ola Dhawe, tetapi telah menyebar ke beberapa dusun di desa tersebut, antara lain di Dusun Bo'asabi, Dusun Bo'arebhe, dan Bo'abe.
“Sejak beberapa dekade lalu, warga secara bertahap pindah ke wialayah dataran di kaki bukit. Karena di Olah Dhawe mereka sulit mendapatkan air,” jelas Sebastianus Suara.
Namun, ketika hendak melakukan rituat adat semua naik lagi ke Ola Dhawe. “Setiap tahun, pada waktu tertentu, kami semua ke sana untuk melakukan ritual adat,” katanya lagi.

Menyambut Bu’e Jawa dan 7 Saudaranya dari So’a
Sebastianus Suara mengisahkan, setelah kematian orang tuanya, Ana Kodha Goru dan Tawa, Wegu menjadi yaitu piatu dan hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Nasib Wegu Ana Ralo berubah setelah ia berhasil ‘menemukan’ Pegu Ga’e, seorang gadis yang nekad terjun untuk menenggelamkan diri di sungai karena merasa malu dituduh berzinah.
Penemuan Penu Ga’e berlangsung secara ajaib, melalui penangkapan seekor ikan besar. Ikan itu kemudian menjelma menjadi seorang gadis cantik dan memperkenalkan diri sebagai Bu’e Jawa.
Wegu Ana Ralo kemudian menikahi Bu’e Jawa itu dan hidup sejahtera. Selain memiliki kebun yang luas dan selalu memberikan panen berlimpah, mereka memiliki hewan ternak, terutama kerbau yang sangat banyak. Sebagai pasutri yang kaya, Wegu dan Bu’e Jawa menyanggupi untuk menangggung seluruh biaya pendirian Peo.
Kemudian, ketika hendak mendirikan Peo, orang Dhawe mencari lalu menemukan kayu Rebu di Pau Lowa, Soa, kemudian menghanyutkannya mendekati Kampung Ola Dhawe lewat aliran sungai.
Pada hari keenam, dalam rangkain upacara “Para Peo” yang dibiayai seluruhnya oleh Wegu dan Bu’e Jawa, Bu’e Jawa sedang menari di halaman rumah. Tiba-tiba datanglah seekor anjing jantan merah menjilat-jilat kaki Bu’e Jawa.
Bu’e Jawa langsung tahu bahwa itu adalah anjing para saudaranya dari So’a. Tak lama kemudian datanglah ketujuh saudaranya dari Soa, berturut-turut dari yang sulung sampai kepada yang bungsu. Mereka dikawali oleh sekelompok orang Talukan dari Poma (Ana Bhui Mara)..
Ketujuh orang saudara Bu’e Jawa itu adalah Lape Ga’e, Tade Ga’e, Gaja Ga’e, Gewo Ga’e, Gera Ga’e, Oba Ga’e dan Eko Ga’e.
Setelah upacara Para Peo berakhir, Bu’e Jawa melantunkan lagu ratapan ang isinya meminta supaya salah satu dari ketujuh saudaranya itu mau tinggal menemani dia di Ola Dhawe.
Sembari menangis Bu’e Jawa berkata kepada para saudaranya: “Miu teo nga’o ne’e riru wigu, bholo ko mo’o dhoko nga’o laza logo. Miu bae nga’o ne’e rara kasa, bholo mo’o su’u nga’o laza ulu” (Artinya: ‘Kamu gantungkan telinga saya dengan emas sampai menyentuh bahu, tapi itu menjadi beban yang terlalu berat sehingga untuk memikulnya saya sakit punggung, Kamu berikan saya dengan banyak perhiasan tetapi untuk menjunjung saya sakit kepala).
Saudara-saudaranya mengerti bahwa ucapan-ucapan yang berupa kiasan itu berarti meminta tenaga bantu karena Bu’e Jawa dan suaminya, Wegu, tidak dikaruniai anak.
Ketujuh bersaudara itu pun berrembuk lalu bersepakat bahwa si bungsu, Eko Ga’e menetap di Ola Dhawe menemani Bu’e Jawa.
Eko Ga’e kemudian diantarkan ke Au Radu, di rumah yang bernama “Kelikisa”. Orang Ola Dhawe menerima Eko Ga’e dan menyerahkan hak adat kepadanya.
Semenjak itu Eko Ga’e menjadi : “Tugu-Tugu Laba Jawa, Ku Ulu Enga Eko” . Ia menjadi penjaga Tugu-tugu (Bendera), Laba Jawa = Gendang, dan Ku Ulu Enga Eko (sebagai komando pasukan).
Kisah ini menegaskan adanya jejaring budaya antara komunitas Dhawe dengan kelompok di So’a, serta interaksi yang bersifat integratif, bukan konflik.
Alur narasi yang penuh kejutan
Alur legenda di atas memang terkesan penuh kejutan bahkan cukup sulit dicerna akal sehat. Apalagi, soal bahtera (kapal besar) Dhawe-Dhengi yang kemudian terdampar di bukit yang kini disebut Ola Dhawe.
Penggalan narasi ini, diduga muncul belakangan, setelah orang Dhawe berkenalan dengan cerita Kitab Suci tentang Kisah Nabih Nuh dan Air Bah.
Penulis Kristen dan Yahudi awal seperti Flavius Josephus percaya bahwa Bahtera Nuh ada, meskipun pencarian Bahtera Nuh yang gagal telah dilakukan setidaknya sejak zaman Eusebius (Tahun 275–339 M).
Orang-orang yang percaya pada keberadaan Bahtera Nuh terus mencarinya di zaman modern. Namun tidak ada bukti ilmiah bahwa bahtera itu pernah ditemukan, juga tidak ada bukti ilmiah tentang air bah atau bencana banjir global.
Kapal dan bencana alam seperti yang dijelaskan dalam Alkitab akan bergantung pada ketidakmungkinan fisik dan anakronisme yang luar biasa.
Beberapa peneliti percaya bahwa peristiwa banjir yang nyata (meskipun terlokalisir) memang pernah terjadi di kawasan Timur Tengah .
Bencana lokal itu adalah banjir Teluk Persia dan Banjir Laut Hitam terjadi 7.500 tahun yang lalu.
Kedua peristiwa alam tersebut diduga telah menginspirasi narasi lisan dan tertulis kemudian, lalu diberi makna spiritual sehingga menjadi kisah suci seperti yang dinarasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama.
Lalu bagaimana dengan nama Kowa Dhawe? Nama ini boleh jadi diinspirasi oleh cerita yang lebih dahulu mengenai kisah kedatangan nenek moyang orang Dhawe. Mereka datang entah dari mana.
Namun, ada kemungkinan mereka datang dari Wio (Sumba) karena nama itu disebutkan dalam syair Teke (Tandak) orang Dhawe.
Penggalan syair itu berbunyi: “Ooo......eaee.... Be-be nio lewa, mara belu molo walo, Poja-poja ana jara Wio, bana pawe ma’e pengi nenu”.
(Artinya: "Ooo …eaee.. Kelapa tinggi walaupun miring (bila ditiup angin) dapat tegak kembali, Jika melatih kuda Wio (Sumba), setelah terlatih jangan melihat bayangan).
Tentu saja, cukup sulit untuk membayangkan bahwa sebuah Kapal Besar (milik Dhawe-Dhengi) terdampar di puncak bukit yang menjadi lokasi Kampung Adat Ola Dhawe sekarang.
Lebih realitis misalnya membayangkan bahwa pada suatu zaman dahulu, debit air Sungai Aesesa -yang melintas tak terlalu jauh dari Ola Dhawe - masih sangat besar, sehingga kapal atau perahu besar bisa masuk hingga ke pedalaman sekitar Malawake sekarang.
Hal ini mungkin dapat diterima, karena -sekadar membadingkan- sekitar 100 tahun lalu, kapal kecil di Pelabuhan Sunda Kelapa bisa masuk hingga 20-an km ke wilayah Depok, sekaran karena debit sungai Ciliwung masih besar dan sedimen material lumpur di dasarnya belum cukup tebal.
Lalu, apakah Dhawe dan Dhengi berasal dari generasi/ras Austronesia yang memasuki wilayah kepulauan Nusantara dari arah utara, Yunan (Taiwan) melaluli Filipina, terus ke selatan pada masa sekitar 6000 hingga 2.500 SM?
Rupanya, tidak! Karena ras Austronesia belum mengenal kapal/perahu besar.
Menurut para ahli sejarah, ras Austranesia menjangkau pulau-pulau di Nusantara secara bertahap dengan rakit sederhana.
Meski demikian, legenda tersebut di atas mengindikasikan bahwa pada zaman lampau orang pribumi Dhawe memang pernah mengalami kontak dengan pendatang dari luar pulau yaitu orang Gowa dan orang Jawa serta dengan warga sedaratan yaitu orang So’a.
Soal urut-urutan kontak, memang cukup membingungkan. Kontak dengan orang So’a digambarkan terjadi belakangan. Tetapi, Bu’e Jawa yang mengindikasikan kontak dengan orang Jawa, digambarkan sebagai seorang wanita yang saudara-saudaranya hidup di So’a.
Sementara itu Ana Kodha Goru yang berasal dari Gowa, digambarkan hadir lebih awal dari Bu’e (orang) Jawa dan orang So’a.
Padahal, yang lebih masuk akal, orang Dhawe seharusnya lebih dahulu ‘berkenalan’ dengan orang So’a. Karena kedua klan itu tinggal tidak terlalu berjauhan. Bahkan, boleh jadi mereka pernah menjelajah kawasan ‘perburuan’ dalam irisan yang sama.
Jika merunut ke sejarah, kontak pertama pribumi Flores dengan orang Jawa (pasukan Patih Gajah Mada, dari Kerajaan Hindu-Majapahit) pada awal tahun atau awal abad ke-14.
Sementara, orang Gowa, diketahui terpencar ke berbagai kawasan Nusantara, termasuk ke Flores, setelah Kerajaan Goa-Talo ditaklukkan Belanda pada than 1669 atau pada paruh kedua abad ke-17.
Bukti-bukti bernilai historis
Meski urutan kontak pribumi Dhawe dengan orang dari luar tak selaras dengan fakta sejarah, generasi sekarang setidaknya memahami bahwa kontak pribumi Dhawe dengan orang So’a, Jawa, dan Goa memang pernah terjadi.
Bahkan, tak tertutup kemungkinan bahwa orang pribumi Dhawe pernah berinteraksi langsung dengan para saudagar dari Cina dan Gujarat (India) yang sudah melalang buana di wialayah Nusantara jauh lebih awal dari orang Jawa-Majapahit.
Buktinya, di Dhawe pernah beredar Piga Sina (Piring Porselen Cina), Pane Sina (Piring Cina yang terbuat dari tanah liat), Tana Sina (Gumbang Cina), Ura Suta (Benang Sutra Cina).
“Dulu di rumah ini ada beberapa Piga Sina. Tapi sudah pecah karena tidak diperlakukan secara hati-hati. Pecahannya sudah di buang entah ke mana,” tutur Sebastianus.
Perihal Benang Sutera, ada dugaan itu tidak langsung dibawa oleh orang Cina, tetapi dibawa oleh dibawa oleh Ana Kodha Goru dari Goa. Sebab dalam pentas seni Teke (Tandak) terdapat syair pantun yang berbunyi: “ Ura suta Sina Goru, Ko na Goru oee.....” (Artinya: “Benang Cina atau benang sutra itu dibawakan oleh Ana Kodha Goru”).

Bukti adanya kontak pribumi Dhawe dengan Kerajaan Majapahit di Jawa ialah Kamu Ke’o, keris milik Wegu Ana Ralo, Peti berukir Sisik Ikan, Tugu-Tugu (Bendera), Laba Jawa (Gendang Jawa), Pane Jawa (Piring dari tanah liat dari Jawa), serta hasil-hasil tanaman seperti Jawa (Jagung), Muku Jawa (Pepaya), Pau Jawa (Mangga). (Bdk. Herman Gebu, Tahun (?): 27).
Sedangkan bukti kontak dengan orang So’a adalah ritual Para Peo dan tugu Peo yang berdiri di Ola Dhawe, karena menurut tradisi lisan diambil dari Soa.
Hal itu mempertegas bahwa tradisi mendirikan Peo memang berasal dari Soa sebagaimana digambarkan oleh komunitas adat lainnya di Nagekeo.
Sementara, bukti kasat mata kontak pribumi Dhawe dengan orang Gowa adalah Bahasa Mbay, adat budaya dan tradisi menenun songket (Lipa Dhowik).
Peti Berukir ‘Sisik Ikan’: Dari Orang Gowa ataukah Orang Portugis?
Tak dapat dipungkiri banyak hal menarik terkait sejarah Dhawe-Mbay. Namun, salah satu yang menurut penulis paling menarik adalah keberadaan Peti ‘tua’ berukir Sisik Ikan.
Memang, sekilas, motif yang terukir di peti tua yang disimpan di rumah Sebatianus Suara di Kampung Malawake, tampak seperti ‘sisik ikan’.
Namun, apabila diamati secara teliti, sebetulnya, ukiran itu bukan berupa sisik ikan, melainkan pola gemotris menyerupai dua ‘lingkaran cahaya’ yang dipadu dengan sejumlah besar ‘salib’ yang dibuat berjejer dan bertebaran di seluruh permukaan peti.
Jadi, peti itu sepertinya menggambarkan alam semesta yang terdiri atas dua bola bercahaya yaitu matahari dan bulan, dan ratusan bintang yang digambarkan berupa ‘salib’.
Ketika ditanya dari mana asal peti tua itu?
Sebastianus Suara secara spotan menerangkan bahwa ‘peti tua’ itu adalah warisan dari nenek moyang. ‘Menurut cerita nenek moyang, (peti ini) berasal dari Gowa’, ujarnya.
Jawaban Sebastianus mengundang ragu. Sebab, menilik pola atau motif tersebut, sangat berat untuk mengaitkannya dengan Gowa.
Sebab, Ana Kodha Goru diduga meninggalkan Gowa karena Gowa Tallo ditaklukkan Belanda tahun 1669.
Waktu itu warga kerajaan Gowa Tallo sudah menganut agama Islam dan dikenal sebagai sebuah kesultan Islam yang berjaya.
Raja Gowa Tallo pertama, Karaeng Matoaya, pemimpinan Kerajaan Tallo (1593-1623) sudah memeluk Islam pada pada Jumat, 22 September 1605 dan diberi gelar Sultan Abdullah Awalul Islam.
Sebagai sebuah kerajaan atau kesultanan Islam, segala tradisi seni-budaya, termasuk seni ukiran sudah tentu bernuansa Islam. Artinya, peti-peti yang dibuat di wilayah Goa memiliki dua peluang, polos (tanpa motif) atau diberi motif dengan kaligrafi: seni menulis ayat Alquran. Bukan, sebaliknya menggambarkan dua buah bola besar bercahaya dan salib-salib kecil yang adalah simbol penting dalam Kekristenan.
Lalu dari mana asalnya motif ‘alam semesta’ pada peti tua di Malawake itu?
Salah satu peluangnya adalah Portugis. Mengapa? Motif-motif pada peti tua itu sangat dekat dengan motif Azulejos, ubin keramik berlapis timah yang dicat indah yang menutupi lantai dan tembok kota-kota Portugis sejak abad ke-12 M.
Ubin keramik dengan motif yang mirip dengan motif yang terdapat pada peti tua Malawake, banyak terlihat di fasad gereja, sekolah, teater, stasiun kereta api atau bangunan penting, tetapi juga di rumah biasa, yang tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa, tetapi mungkin milik keluarga kaya di masa lalu.

Banyak orang mengira bahwa kata "azulejo" berhubungan dengan "azul", yang berarti biru dalam bahasa Spanyol dan Portugis.
Memang benar bahwa sebagian besar ubin Portugis yang terkenal berwarna biru, tetapi asal kata sebenarnya berasal dari Bahasa Arab ‘azzelij’ (atau al zuleycha, al zuléija, al zulaiju, al zulaco) yang berarti "batu kecil yang dipoles".
Ini adalah teknik yang sudah digunakan selama Zaman Kuno di Mesir Kuno dan Mesopotamia, tidak hanya untuk keperluan dekorasi, tetapi juga untuk melindungi bangunan dari iklim hangat di wilayah ini.
Azulejo dengan demikian adalah salah satu dari banyak jejak yang ditinggalkan oleh bangsa Moor di Semenanjung Iberia.
Saat itu, Azulejo terdiri dari mozaik ubin keramik berwarna yang dipotong dalam bentuk geometris dan disatukan untuk membentuk pola. Contoh yang sangat terkenal dari teknik ini masih bisa dilihat di Alhambra di Granada.
Baru pada tahun 1503, setelah berkunjung ke Sevilla, Raja Manuel I memperkenalkan Azulejo ke Portugal. Negara pertama terus bergantung pada ekspor dari negara lain.
Sementara itu, di Italia, seniman mempersonalisasi produksi Azulejo mereka dan mulai menggunakan ubin sebagai dasar untuk melukis adegan alkitabiah.
Ini memiliki pengaruh besar pada apa yang kemudian menjadi seni khas Portugis.
Memang, pada abad ke-15 dan ke-16, azulejo Portugis diproduksi secara massal.
Selanjutnya, motif Azulejo beredar meluas ke Brasil dan koloni lainnya termasuk di Nusantara, bukan hanya pada keramik, tetapi juga dikenakan pada peralatan berharga lainnya seperti perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari dan peti.
Upaya ekonstruksi Lisbon pasca- gempa bumi tahun 1755 memunculkan peran dekorasi yang lebih bertalian dengan Azulejos, dan warisannya terlihat hingga saat ini di ibu kota Portugis itu.
Saat ini Museu Nacional do Azulejo di Lisbon menyimpan koleksi ubin Portugis terbesar di dunia. Barangkali kebetulkan saja, motif Azulejos, ternyata sarat dengan simbol-simbol yang akrab di kalangan gereja Katolik.
Itu sebabnya, motif-motif tersebut dianggap sebagai hal yang ikut mewarnai dan memperkuat misi gereja Katolik ke seluruh dunia, apalagi di wilayah Islam, sebagai ‘aksi pembalasan’ atas kekejaman bangsa Moor yang pernah menguasai Portugis dan Spanyol.
Makanya, dalam arsip misi, banyak terlihat bahwa peti-peti yang dipakai para misionaris Dominikan Portugis ke berbagai wilayah Misi di Afrika, India, Amerika Latin hingga Flores, Timor, Maluku, terdapat sejumlah gambar peti dengan motif yang mirip dengan motif pada peti tua di Malawake itu.
Pada gambar di bawah ini, tampak pada sisi kiri atas adalah peti yang digunakan para misionaris Portugis pada abad ke-15. Di sebelah kanannya adalah peti misionaris Portugis pada abad ke-16.
Meski tampak samar-samar, pada bagi depan di dua peti tersebut tampak dua pola lingkaran seperti bola bercahaya.
Sementara itu, yang atas paling kanan adalah gambar kain penutup piala Misa Kudus. Gambar salib di kain itu tampak identik dengan gambar ‘salib’ pada peti tua Malawake.
Gambar kiri bawah adalah peti tua yang ada di sebuah lokasi di Yogyakarta. Gambar lingkaran tampak sangat mirip dengan lingkaran besar pada peti tua di Malawake di sebelah kanannya.

Diduga, peti tua yang di Yogyakarta dan di Malawake itu berasal dari para misionaris Portugis yang hidup pada abad ke-17. Makanya, dekorasinya tampak lebih kaya dan lebih teliti dari peti serupa yang berasal dari abad ke-15 dan 16.
Bagaimana peti tua itu bisa sampai ke tangan pribumi Dhawe? Itu pertanyaan yang perlu digali.
Kalau benar itu datang melalui tangan orang Gowa, itu berarti peti tersebut adalah hasil rampasan dari para misionaris Portugis.
Atau bisa saja terjadi, peti itu adalah rampasan Belanda dari tangan orang Portugis yang kemudian jatuh ke tangan orang Gowa.
Sebab, pada saat tertentu di abad ke-17 (sekitar 1630-an), sebelum menaklukkan Gowa-Talo, Belanda juga bergandengan tangan dengan kaum Muslim untuk bersama-sama menyingkirkan orang Portugis di Solor, Pulau Ende, Tonggo, dan Timor.
Begitulah dugaan soal lika-liku ‘perjalanan’ mengapa peti tua bermotif ‘alam semesta’ akhirnya tedampar di rumah Sebastianus Suara di Malawake, Dhawe.
Sebuah ‘kisah perjalanan’ yang menarik bukan? *** (Maxi Ali).