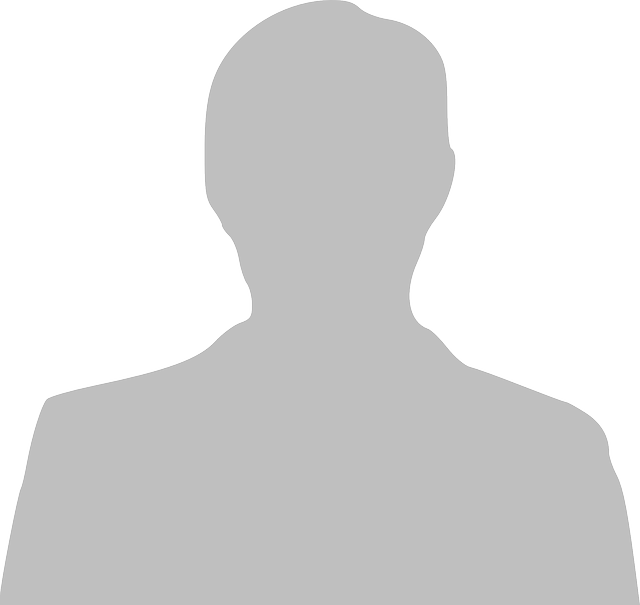OPINI: Digitalisasi Perpajakan: Antara Transparansi dan Kerentanan Penipuan
redaksi - Senin, 18 Agustus 2025 18:21 Ilustrasi: Digitalisasi pajak. (sumber: winpartners.id/blog)
Ilustrasi: Digitalisasi pajak. (sumber: winpartners.id/blog)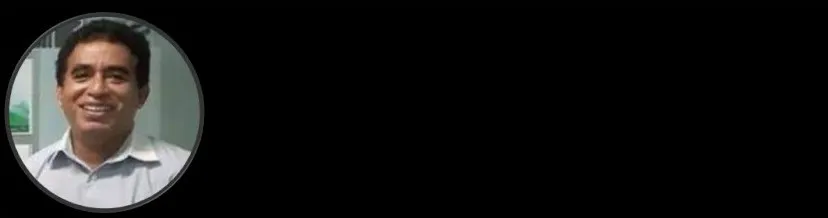
Oleh: Maximus Ali Perajaka*
BELUM lama ini, seorang rekan di grup WhatsApp alumni membagikan peringatan: “Kalau ada link pajak masuk, jangan dibuka. Tadi pagi, teman saya kehilangan Rp46 juta karena nomor ponselnya terhubung ke m-banking. Mohon waspada, silakan teruskan ke keluarga dan komunitas masing-masing.”
Kisah sederhana itu memberi gambaran nyata bahwa dunia perpajakan digital kita sedang menghadapi ancaman serius.
Pajak sendiri merupakan penopang utama keuangan publik dan stabilitas ekonomi nasional. Pada 2024, lebih dari 80 persen APBN bersumber dari penerimaan pajak, dan untuk 2025 target penerimaan ditetapkan lebih dari Rp2.300 triliun—sekitar delapan persen lebih tinggi dibanding realisasi sebelumnya (Kemenkeu, 2024). Dengan digitalisasi yang semakin masif, pemerintah berharap tax ratio naik dari 10 persen PDB di 2024 menjadi 12 persen pada 2027 (OECD, 2023).
Janji Transparansi vs Realita Penipuan
Didorong oleh ambisi menjadi pusat kegiatan ekonomi digital Asia–Pasifik, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia terus meningkatkan investasi pada infrastruktur digital. Pada tahun 2024, kapasitas pasar pusat data nasional yang AI-ready mencapai 743 MW dengan nilai mencapai hampir US$4 miliar (Kompas.com, 2025).
Dari sisi konektivitas, jaringan 4G masih mendominasi dengan cakupan sembilan puluhan persen. Namun, pemerintah terus memberikan insentif agar adopsi 5G dapat meluas setelah tahun 2027 (Kemkeu, 2025).
Untuk memperkuat koneksi internasional, proyek kabel bawah laut bersama Google dan Meta digarap, bersamaan dengan perluasan Palapa Ring dan MyRepublic untuk memperluas akses broadband hingga pelosok nusantara (Kompas.com, 2025).
Selain menggunakan APBN sebesar Rp75 triliun pada periode 2019–2022, pemerintah juga menggandeng pihak swasta dan lembaga keuangan. Contohnya, aliansi INA–Granite Asia menanamkan investasi lebih dari US$1 miliar, sedangkan bank menyalurkan pinjaman lebih dari Rp6 triliun untuk pembangunan kampus pusat data berkapasitas 72 MW di Batam (Kemkeu, 2025).
Dukungan bagi transformasi digital juga datang dari raksasa global seperti Microsoft, Tencent Cloud dan Alibaba Cloud. Dukungan itu dengan nilai triliunan rupiah itu berlangsung secara bervariasi, antara tahun 2030 dan 2033.
Bertolak dari fenomena kemajuan infrastruktur digital tersebut, pemerintah optimistis dapat mengakselerasi penerapan e-filing, e-billing, e-faktur, serta integrasi data perpajakan. Digitalisasi ini diyakini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat transparansi dan efisiensi administrasi fiskal (Kemkeu, 2025).
Hasil awal mulai terlihat. Sampai awal April 2025, Direktorat Jenderal Pajak melaporkan belasan juta wajib pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2024. Mayoritas SPT disampaikan lewat sistem elektronik, hanya sebagian kecil yang masih manual (DJP, 2025).
Meskipun mendorong efisiensi dan memperbaiki kepatuhan, digitalisasi tetap menghadirkan sisi gelap berupa maraknya praktik penipuan dan manipulasi.
Kajian Tax Justice Network tahun 2020 menunjukkan Indonesia berada di posisi keempat di Asia dalam hal praktik penghindaran pajak, dengan potensi kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.
Selain itu, persoalan kebocoran data juga serius. Sepanjang Januari–September 2024, tercatat jutaan data NPWP dilaporkan beredar di internet (Antara, 2024). Fenomena ini mencerminkan lemahnya regulasi perlindungan data di sektor publik.
Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, pola penipuan digital yang menyasar wajib pajak terus berevolusi: mulai dari surat palsu bergaya resmi yang menipu dengan iming-iming buku pajak, phishing melalui laman e-filing tiruan, pesan WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat pajak, hingga aplikasi ‘M-Pajak’ versi palsu berbasis APK berbahaya (DDTC, 2022; DDTC, 2023; Antara, 2024; Pajak.com, 2025).”
Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa meskipun digitalisasi perpajakan menjanjikan transparansi dan efisiensi, realitasnya ia juga membuka ruang bagi kecurangan baru. Sistem yang semula dirancang untuk memperkuat kepercayaan publik justru menghadirkan tantangan serius dalam bentuk penghindaran pajak, kebocoran data, dan penipuan digital.
Dua Titik Lemah Utama
Paradoks digitalisasi perpajakan di Indonesia justru lahir dari dua persoalan mendasar.
Pertama, kerentanan keamanan siber nasional. Laporan Kaspersky (2023) menempatkan Indonesia sebagai salah satu target serangan siber terbanyak di Asia Tenggara.
Temuan tersebut memberi sinyal bahwa sistem perpajakan, sebagai komponen vital dalam arus keuangan negara, sudah seharusnya mendapat perlindungan setara dengan infrastruktur pertahanan strategis.
Tanpa penguatan keamanan siber, transformasi digital perpajakan akan selalu dibayang-bayangi risiko kebocoran data dan manipulasi.
Kedua, lemahnya literasi digital wajib pajak. Banyak pelaku UMKM maupun individu masih kesulitan membedakan email resmi dengan phishing, atau aplikasi otentik dengan file APK berbahaya. Kondisi ini menjadikan masyarakat mudah diperdaya para penjahat digital.
Kementerian Koperasi dan UKM (2021) mencatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 63 juta, dengan mayoritas berupa usaha mikro. Namun, hanya sebagian kecil -sekitar 27 persen- yang sudah mengadopsi teknologi digital dalam menjalankan bisnisnya.
Kesenjangan tersebut semakin ditegaskan oleh temuan Asosiasi UMKM Indonesia (2022), yang mencatat sekitar 70–80 persen UMKM di Indonesia bahkan belum melek digital sama sekali, termasuk belum menggunakan platform e-commerce. Artinya, digitalisasi perpajakan menghadapi tantangan ganda: infrastruktur yang rapuh di satu sisi, dan kapasitas wajib pajak yang terbatas di sisi lain. Tanpa intervensi kebijakan yang serius, dua titik lemah ini dapat menjadi pintu masuk bagi serangan siber sekaligus menghambat tercapainya kepatuhan pajak yang adil dan transparan.
Belajar dari Pengalaman Global
Sejatinya, digitalisasi perpajakan tidak bisa berjalan sendiri. Untuk menghasilkan dampak yang optimal, kita perlu belajar dari jejak transformasi digital di sektor publik maupun bisnis di berbagai negara yang sudah lebih dulu membuktikan keberhasilannya.
Dari negara tetangga, Singapura misalnya, kita bisa belajar bahwa digitalisasi perpajakan dapat dipadukan dengan sistem peringatan dini terhadap penipuan daring, dan program edukasi publik masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (OECD, 2021).
Kita juga dapat belajar dari Estonia atau ‘E-Estonia’. Negeri dengan jumlah ‘unicorn’ terbanyak didunia ini menerapkan sistem e-Tax yang memungkinkan 98–99 persen formulir SPT diisi dan disampaikan secara dalam beberapa menit.
Transformasi ini didukung oleh infrastruktur e-Governance terintegrasi, keamanan siber yang kuat dan literasi digital yang tinggi, membuat administrasi pajak efisien, transparan, dan minim potensi manipulasi. (IMF 2025; e-Estonia).
Kita juga bisa mengambil pelajaran penting dari Inggris dan Amerika Serikat. Melalui program Making Tax Digital, Inggris terbukti berhasil mengurangi potensi kekeliruan yang biasanya muncul dari pelaporan manual, sekaligus membuat administrasi perpajakan lebih presisi. Sementara itu, Amerika Serikat diketahui menggunakan analitik data canggih untuk mendeteksi pola penghindaran pajak dengan lebih cepat dan efisien, (IRS, 2022).
Dari kasus-kasus ini tampak jelas bahwa digitalisasi pajak tidak boleh berhenti pada penyediaan platform layanan, melainkan harus diwujudkan sebagai ekosistem yang aman, transparan, dan berkeadilan.
Jalan ke Depan
Transformasi digital perpajakan di Indonesia menuntut strategi yang matang agar tidak berubah menjadi bumerang. Digitalisasi bukan semata urusan teknis, melainkan menyangkut etika, keadilan, dan keberlanjutan sistem keuangan negara.
Pertama, diperlukan refleksi kritis mengenai etika berteknologi digital. Implementasi perpajakan berbasis teknologi harus selaras dengan amanat konstitusi UUD 1945 dan nilai Pancasila yang menjunjung kemanusiaan, gotong royong, dan keadilan sosial.
Tantangan yang patut diwaspadai adalah potensi ketidakadilan: perusahaan besar yang memiliki sumber daya hukum dan teknologi bisa memanfaatkan celah regulasi, sementara pelaku UMKM justru terbebani kepatuhan penuh.
Di sinilah relevan gagasan Hans Jonas (1979) tentang Etika Tanggung Jawab, yang menegaskan bahwa teknologi harus dikendalikan moralitas demi melindungi martabat dan hak-hak manusia, termasuk hak untuk mendapat keadilan di bidang ekonomi.
Kedua, Indonesia perlu memperkuat sistem keamanan siber nasional. Sistem pajak harus diperlakukan sebagai infrastruktur kritis negara, sehingga terlindungi dari peretasan, kebocoran, maupun manipulasi data.
Ketiga, pemerintah harus meningkatkan literasi digital pajak bagi UMKM dan masyarakat luas. Dengan pemahaman yang memadai, partisipasi mereka akan lebih maksimal dan risiko kesalahan administrasi dapat ditekan.
Keempat, diperlukan audit independen dan mekanisme check and balance agar transparansi dan akuntabilitas berlaku tidak hanya untuk wajib pajak, tetapi juga bagi negara sebagai pengelola pajak.
Kelima, regulasi perlindungan data pribadi harus dijalankan secara konsisten. Implementasi UU PDP (2022) menjadi kunci untuk menjaga privasi, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan ekosistem perpajakan digital yang sehat.
Nah, apabila langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, digitalisasi perpajakan akan menjadi bukan sekadar alat efisiensi, melainkan pilar keadilan dan keberlanjutan bagi Indonesia. (*)
*Praktisi di bidang pendidikan dan media. ***