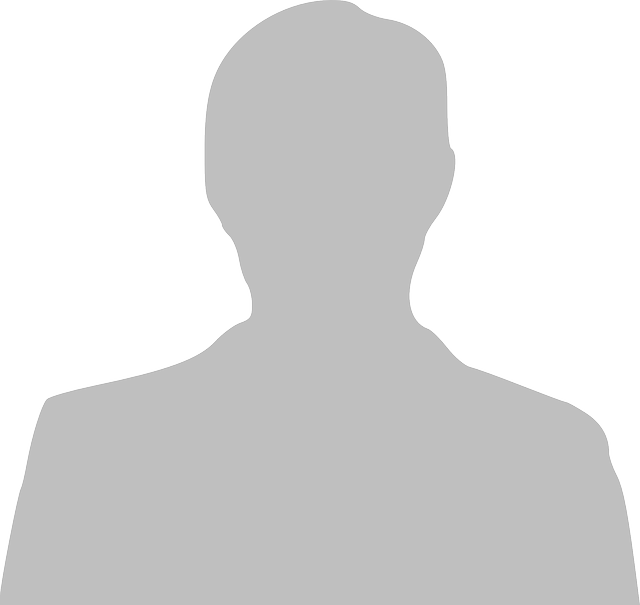TPPO di Flobamora, ‘Warisan Sejarah’ Perdagangan Budak Masa Silam? (Bagian Kedua)
redaksi - Sabtu, 29 Maret 2025 16:21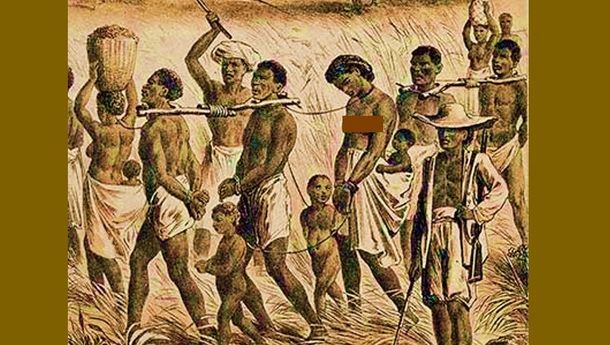 Ilustrasi: Perbudakan pada zaman kuno (sumber: Steve Braker Book)
Ilustrasi: Perbudakan pada zaman kuno (sumber: Steve Braker Book)Oleh: Maxi Ali Perajaka
AKHIR Desember 2024 lalu, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan telah menangani 16 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) TPPO (human trafficking) sepanjang tahun 2024.
Dari belasan kasus TPPO itu, 10 di antaranya diserahkan ke pengadilan, sementara 6 kasus lainnya dalam tahapan penyidikan.
Dirreskrimum Polda NTT Kombes Patar Silalahi menyebutkan dalam kasus TPPO itu delapan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan korban berjumlah 39 orang. Para pelaku melancarkan aksi mereka dengan merekrut pada korban untuk dipekerjakan ke luar negeri dengan janji upah besar. (Bdk. Detik.com, 24 Desember 2024).
TPPO adalah masalah yang ruwet, yang tidak muncul serta merta, melainkan memiliki latar belakang sosial-budaya dan historis yang panjang.
Sekilas gambaran tentang erdagangan budak pada zaman kuno
TPPO yang bermula dari perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak, dan mencakup lintas pulau dan benua. Jenis tindakan kriminal ini telah berubah seiring waktu, beradaptasi dengan dinamika sosial-ekonomi global, dan kemajuan teknologi.
Sejarah mencatat, perdagangan budak telah dpraktikkan sejak zaman kuno. Dalam peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno, budak diperdagangkan untuk memenuhi pasokan tenaga kerja d bidang layanan rumah tangga, buruh tani, dan proyek konstruksi skala besar seperti piramida dan kuil.
Pada era Yunani kuno, khususnya di Athena, budak dipekerjakan di sektor rumah tangga, tambang, dan sebagai pendayung di kapal.
Pada era Kekaisaran Romawi, pada umumnya budak diambil dari para tawanan perang. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pengrajin, pekerja pabrik, pekerja bangunan, pendayung di kapal dan dimanfaatkan sebagai gladiator, peratung yang dipertontonkan di
Dalam berbagai bentuk perbudakan sudah berkembang di berbagai suku Afrika. Budak Afrika dimiliki oleh keluarga bangsawan. Mereka kemudian diperdagangkan bak hewan ternak untuk digunakan sebagai pekerja rumah tangga, pendayung kapal, dan tentara.koloseum.
Di Timur Tengah, perbudakan sangat marak dipraktikkan sejak abad ke-7, terutama pada pada era kejayaan Islam 750-1517 M. Kala itu budak digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai tentara (Mamluk di Mesir), pembantu, dan buruh pertanian dan bangunan.
Di benua Amerika, khususnya pada era peradaban pra-Columbus, suku bangsa Indian seperti Aztec dan Maya mempraktikkan perbudakan juga. Mereka mengekspolitassi para budak untuk bekerja di ladang, sebagai kurban persembahan kepada dewa-dewi, dan sebagai ‘barang gadai’ atau pun alat pembayaran utang.
Selama abad Pertengahan, perbudakan merupakan praktik yang sangat biasa di kalangan bangsa-bangsa Eropa . Di sana para budak umumnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja di ladang.
Perbudakan dalam berbagai bentuk juga terjadi di kawasan Asia seperti di India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, budak umumnya adalah mereka yang kalah dalam peperanan dan menjadi tawanan, atau mereka yang lahir dari kasta rendah.
Perdagangan budak Atlantik (antarbenua) dimulai sekitar tahun 1336 atau 1341, ketika pedagang Portugis membawa budak Canaria pertama ke Eropa.
Pada tahun 1526, pelaut Portugis membawa muatan kapal pertama budak Afrika ke Brasil di Amerika, yang kemudian menjadi awal mula perdagangan budak Atlantik yang bersifat segitiga.
Perdagangan budak di Nusantara zaman pra-kolonialisme
Meski informasinya sangat terbatas, perbudakan dan perdagangan budak di kepulauan Nusantara sudah berkembang sejak zaman kuno.
Konon, praktik tersebut lazim terjadi di negara-negara Hindu-Buddha kuno yang besar seperti Kerajaan Kutai (400–1635), Sriwijaya (671–1028), Mataram Kuno (716–1016), Kerajaan Kahuripan (1019–1046), Kerajaan Janggala, (1042–1135), Kerajaan Kadiri (1042–1222) Kerajaan Singasari (1222–1292), dan Kerajaan Majapahit (1293–1478).
Para sejarahwan juga menduga bahwa praktik perbudakanan dan perdagangan budak juga sudah lumrah terjadi di kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara seperti kerajaan-kerajaan di Sumbawa, di Nusa Nipa, Sumba, Timor, alor, Kei, Papua, Maluku dan Sulawesi.
Dalam konteks ini, biasanya yang menjadi budak adalah para prajurit (kaum lelaki) dari faksi yang kalah berperang.
Mereka kemudian ditawan, dipekerjakan sebagai buruh kasar atau dijual sebagai budak. Sedangkan kaum wanitanya ditawan dan dipekerjak sebagai pembantu rumah tangga dan yang masih muda diperlakukan sebagai pelayan seks. Keturunan mereka kemudian dianggap sebagai budak juga.
Meski demikian informasi mengenai perbudakan dan perdagangan budak di zaman kuno hingga abad ke-13 relatif sangat minim.
Namun, sebagaimana berlaku di kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Tenggara, perbudakaan di pada era ini meliputi dua sistem yaitu "tertutup" dan "terbuka", dan contoh lain yang tampak berada di antara keduanya. (Bdk. Antony Reid, 2017).
Sistem perbudakan "tertutup" dapat didefinisikan sebagai sistem yang berorientasi terutama untuk mempertahankan tenaga kerja budak dengan memperkuat kekhasan mereka dari populasi yang dominan.
Pola ini biasanya terjadi di masyarakat yang relatif statis dan mandiri yang mempraktikkan pertanian padi sawah yang padat karya, di mana pertukaran komersial dan ekonomi uang tidak banyak berdampak.
Meskipun budak dianggap sebagai properti dalam konteks ini, hanya ada sedikit pertukaran dalam praktiknya (Bdk. Antony Reid, 2017).
Pada sisi lain, sistem "terbuka" adalah sistem yang memperoleh tenaga kerja melalui penangkapan/penculonan atau pembelian budak, dan secara bertahap mengasimilasi mereka ke dalam kelompok dominan.
Para budak yang baru saja diperoleh juga merupakan budak yang paling jelas batasnya, dan perekrutan mereka yang terus-menerus membuat tidak perlu lagi menekankan status budak generasi kedua dan ketiga. (Bdk. Antony Reid, 2017).
Kemudian ketika kerajaan Hindu-Budha meredup dan bertransformasi menjadi kesultanan Islam selama abad ke-15, perbudakan dan perdagangan budak memiliki karakteristik yang sama dengan perbudakan di seluruh dunia Muslim karena dikelola menurut syariat Islam.
Artinya, perdagangan budak merujuk ke praktik perdagangan budak yang terjadi pada era puncak kejayaan Islam di Turki pada abad 14 M seperti digambarkan Simon Webb sebagai berikut:
“Pada tahun 1380-an sistem devshirme mulai diberlakukan. Selama devshirme, sebuah kata yang berarti pengumpulan atau panen, perwakilan sultan menjelajahi Yunani dan Balkan setiap lima tahun, dengan tujuan mengambil anak laki-laki yang sehat dan cerdas berusia antara delapan dan 14 tahun. Mereka diculikdari keluarga mereka dan dibawa ke perbudakan di Konstantinopel, di mana mereka disunat dan kemudian diarahkan masuk agama Islam.
Perlu dicatat sekali lagi, orang Slavia-lah yang menjadi korban penyerbuan budak, karena itulah yang sebenarnya terjadi pada devshirme.
Anak-anak tersebut diculik dari negara-negara yang saat ini merupakan Serbia, Bosnia, Kroasia, Slovenia, Albania, Makedonia, Bulgaria, [Hongaria, Georgia,] dan Yunani…. Begitu mereka berada di Konstantinopel, anak laki-laki yang dikumpulkan dalam devshirme dididik dan berasimilasi dengan kuat ke dalam budaya Turki.” (Bdk. Timothy A. DuskinSeptember 2, 2024).
Pola yang kurang-lebih serupa terjadi dalam praktik perbudakan ketika kesultanan Islam bermunculan di Nusantara pada abad 14-15.
Pada masa ini para bajak laut/pedagang yang mengafisilisikan dirinya dengan agama Islam menyasar anak-anak non-Muslim untuk diperdagangan sebagai budak.
Mereka menculiknya dari berbagai daerah terpencil kemudian menjualnya untuk kepentingan Kesultanan Islam yang sedang berlomba-lomba memperkuat kekuasaan, dan memperluas wilayah pengaruhnya. (Bersambung). ***