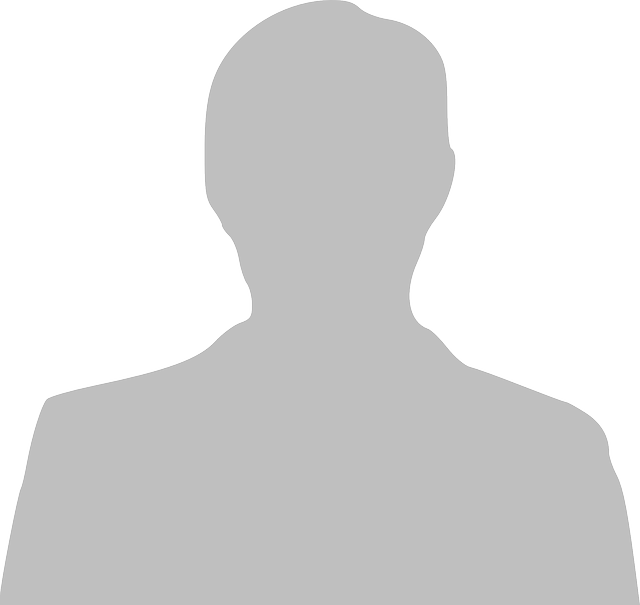Nipa Do ‘Pahlawan’ Tana Toto, Tak Hanya Pemberani, Tapi Juga Cerdik
redaksi - Senin, 11 Agustus 2025 21:48 Bupati Nagekeo periode 2018-2013, Yohanes Do Bosco Do memasang lilin di atas Nabe, sebuah batu lempeng yang dipercaya sebagai tempat duduk pahlawan Nagekeo, Nipa Do di Wodo Wae, Jumat, 02 Oktober 2020. (sumber: :faktahukum.com melalui Floresku.com)
Bupati Nagekeo periode 2018-2013, Yohanes Do Bosco Do memasang lilin di atas Nabe, sebuah batu lempeng yang dipercaya sebagai tempat duduk pahlawan Nagekeo, Nipa Do di Wodo Wae, Jumat, 02 Oktober 2020. (sumber: :faktahukum.com melalui Floresku.com)JELANG HUT ke-80 Kemerdekaan RI , tim redaksi Floresku.com menurunkan ‘Seri Pahlahwan Lokal’, dari wilayah Flobamora. Meski tidak dikenal secara nasional, para pejuang ini telah berjuang secara gagah dan berani, membela martabat warga masyarakat lokal dari kesewenangan kaum kolonial, Hindia-Belanda.
Tana Toto, Negeri Para Pemberani
Tana Toto—tanah leluhur Kunu Toto dengan batas-batas adat yang ditetapkan sejak era nenek-moyang, belasan generasi lalu. Wilayah ini diapiti oleh bentangan Laut Flores di utara, dan bentangan Laut Sawu di selatan.
Di sisi kanan (timur) ada semacam garis/jalur dari utata: Tana Kebi (Desa Kebirangga) di utara dan Numba. Lintasan dari utara ke selatan mencakup Nanga Nio Niba, Kota Kadhe, Goa Poka, Ngi’i Bela, Lange Tana, Kedi Watu Manu, Seararo, Keka, Rere Nggase, hngga Rate Rengge (dekat desa Basa Numba) di selatan.
Sementara itu, di sisi kiri (barat) ada semacam garis atau jalur dari utara: Nage Lewa–Dhangi Tana, Wolo Pau, Phoa Keka–Dowo Dapho, Boa Nai, dan Watu–Paro Re’e di selatan.
Namun, peta adat seakan tercabik ketika pemerintah Hindia-Belanda menerapkan politik divide et impera—memecah wilayah menjadi dua wilayah administrasi.
Tana Toto bagian bagian barat, mulai dari Toto Wolowae di utara, hingga Toto-Ute di selatan masuk dalam wilayah Swapraja Nagekeo.. Sedangkan Tana Toto bagian timur yaitu Toto Tana Jea (Rea)- mulai dari Kaburea di utara hingga Nangapanda-Numba di selatan, masuk wilayah Swapraja Ende.
Sikap Kritis, Dasar Perlawanan Kunu Toto
Menurut catatan sejarah kolonial, demi memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka di wilayah kepulauan nusantara, pemerintah Hindia Belanda memang melakukan dua ekspedisi ke Flores, yaitu pada tahun 1850, dan 1890 di bawah pimpinan.
Namun, aksi pendudukan atas wilayah Flores baru terjadi mulai Juli 1907. Hanya dalam tempo lima bulan, dari Juli hingga Desember, pemerintah Hindia-Belanda melalui pasukan militernya ( 8 brigade Marsose) yang dipimpin Kapten H. Christofeel dengan cukup mudah mematahkan perlawanan-pelawanan di Ende, Ngada dan Manggarai.
Setelah pensiun tahun 1910, Kapten H. Christofe yang dikenal ‘buas’ digantikan oleh asisten-asistennya antara lain Letnan G.D Sapander, Letnan Saragouw dan Saymina. Sedangkan kontrolur pertama yang berkedudukan di Ende yakni A.Covreur, pada tahun 1909, digantikan oleh A.Hens. Ia kemudian naik kedudukannya sebagai Resident-assistent afdeeling Flores di Ende. Ia juga pernah menjabat sebagai gezaghebber (pemegang otoritas) di Ende adalah van Suchtenlen.
Aksi pendudukan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang berkedudukan di Ende membawa perubahan sosial-budaya signifikan. Semenjak ‘takluk’, sistem pemerintahan adat dilemahkan, misi agama dipercepat, pajak berlakukan, dan pendidikan Barat diperkenalkan.
Selaikan melakukan pendudukan secara militer, pemerintah Hindia-Belanda juga memberlakukan sistem pemerintahan yang selaras dengan tujuan politik dan ekonominya.
Dalam memori penyerahan jabatan Controler Onderafdeling Ende, J.F. Strock tertulis, “Sesudah menduduki daerah dan seluruh peolosok di Onder-afdeeling Ende dan Ngada, pemerintah Hindia-Belanda bermaksud membentuk Zelfbesturend (Swapraja) dengan maksud memudahkan pengontrolan.
Berkenaan dengan itu, pemerintah Hindia--Belanda sengaja mengangkat para pihak yang tunduk pada kemauannya menjadi Kepala Swapraja (Raja). Sebaliknya Kepala Suku/Kampung yang ‘bandel’ ditempatkan pada posisi yang lebih renda sebagai Kepala Hamente.
Mengetahui rencana pemerintah Hindia-Belanda membelah Tana Toto ke dalam dua wilayah Swapraja, dan hendak menempatkan dirinya hanya sebagai Kepala Hamente Wolowae, bawahan dari Swapraja Boawae, Nipa Do marah besar.
“Saya yang seharusnya mengangkat Anda menjadi pemimpin di wilayah saya. Bukan sebaliknya, Anda yang mengangkat saya.” Jawab Nipa Do kepada pejabat pemerintah Hindia-Belanda di Ende.
Nipa Do dan para kepala kampung/pemuka adat di Tana Toto menjadi semakin geram ketika menyaksikan dengan mata kepala sendiri sendiri bagaimana warganya dicambuki oleh para serdadu Hindia-Belanda kalau lalai membayar pajak.
Mereka juga menyaksikan dengan hati perih, betapa para pekerja rodi di jalan trans-Flores yang dimulai pada tahun 1912, dipukuli hingga babak belur karena tidak bekerja sesuai dengan arahan para mandor proyek.
Kala itu rakyat Kunu Toto mendapat tugas ikut membuka jalur Ende – Nangaroro yang secara topogragis sangat sulit, karena melintasi tebing berbatu cadas.
Beberapa hal tersebut di atas mengobarkan api perlawanan Kunu Toto, sehingga pada Agustus 1906 pecahlah perang, yang kemudian dikenal sebagai Perang Watuapi (Agustus 1916– Februari 1917).
Jadi, perlawanan Kunu Toto terjadi bukanlah letupan emosi spontan. Perlawanan itu lahir karena sikap kritis terhadap pemerintahan kolonial yang memeras dan memecah belah serta ‘memperkosa’ nilai-nilai adat istiadat para nenek moyang Kunu Toto.
Tokoh-Tokoh Perlawanan: Keberanian yang Memotivasi
Nipa Do adalah pemimpin yang tak hanya gagah dan berani, tetapi juga cerdas dan berwibawa. Ia mampu menggerakkan, mengoordinasi para kepala kampung dan pemuka adat lainnya sehingga siap melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia- Belanda.
Begitu rapinya koordinasi yang dilakukan Nipa Do sampai-sampai sejarawan Jerman Stefan Dietrich mencatat bahwa Perang Watuapi adalah “perlawanan dengan koordinasi paling rapi dibandingkan dengan semua perlawaan rakyat di seluruh Flores. Pasalnya, dalam Perang Watuapi, semua pejuang sangat berdisiplin, dan sangat cerdik dalam melakukan taktik gerilya.” (Bdk. Stefan Dietrich, Kolonialismus und Mission auf Flores, Klaus Renner Verlag, 1989)
Perang Watuapi menjadi semakin luar biasa lantaran dikomandai oleh tokoh-tokoh perlawanan yang berani dan cerdas memotivasi seluruh Kunu Toto untuk ikut berpartisipasi. Perlawanan rakyat Kunu Totoa menyebar ke seluruh wilayah Tanah Toto, mulai dari Watuapi, Wodo We, Malidewa, Kedi Dutja, Koekobho, Dia Bhui, Madasela, Watu Wake Teo Kodo hingga Nangapanda.
Di pucuk pimpinan berdiri Nipa Do yang penuh kharisma dan piawai mengatur strategi perang. Bawahannya adalah tiga panglima lapangan yang tak kalah gagah berani dan cerdasnya.Mereka adalah Datja Dhosa, Kepa Biu, dan Deru Gore.
Di utara, Datja Dhosa memimpin pasukan penjaga gerbang Watuapi. Berbekal keterampilan berburu rusa, sapi, dan kerbau liar, Datja Dhosa dan anak-anak buah membuat para serdadu selalu kerepotan.
Sembari melekat di atas punggung kuda, mereka melintasi bukit savana dan menelusuri lembah serta aliran kali mati, dengan kecepatan tinggi .
Mereka menerobos di antara semak belukar dari arah yang tak terduga. Lalu, secepati kilat mereka menghujamkan tombak dengan presisi tinggi, menumbangkan setiap serdadu Hindia-Belanda yang lengah dan kurang waspada.
Kepa Biu dibantu Wani Ghode yang bertugas mengawal wilayah Toto bagian tengah dan selatan tak pernah kehabisan akal untuk membatasi pergerakan musuh.
Sementara itu Deru Gore memimpin dari arah timur. Ia mengatur serangan mendadak dari hutan dan semak belukar, medan yang sulit dipetakan lawan.
Pertempuran terasa tanpa jeda. Para serdadu Belanda yang dilengkapi senjata api laras panjang, memang memiliki keunggulan secara teknis. Akan tetapi para pejuang Toto yang menguasai medan, mampu mengendalikan pertempuran dengan taktik gerilya yang efektif.
Alhasil, korban tewas dari pihak Hindia-Belanda, jumlahnya mencapai ratusan. Menurut catatan sejarawn P.H. Doko, para serdadu Hindia-Belanda yang tewas dan dikuburkan secara massal di Kampung Malasera, sekitar 200 orang.
Namun, tak dapat dimungkiri, korban dari pihak Kunu Toto tidak sedikit. Bahkan, para pemimpinnya gugur satu demi satu.
Melalui bantuan sekelompok orang pengkhianat, Nipa Do sendiri kemudian terperangkap lalu terbunuh oleh peluru musuh. Ia kemudian dimakamkan Bukit Nusa Padha Yaca.
Sangu Papu, tangan kanan Deru Gore dari Tana Rea (Djea) juga ditangkap, lalu dibuang dan dipenjarakan selama 10 tahun di Singapura,
Kepa Biu yang berbasis di Koekobho juga ditangkap dan ditembak mati. Kematian Kepa Biu menaikkan semangat rakyat — dan mengguncang hati istrinya, Ine No’o.
Wanita itu pun naik ke punggung kuda, memimpin pasukan melakukan serangan yang menakutkan—berani dan murni membuktikan bahwa keberanian bukan monopoli laki-laki. Sampai akhir hayatnya, ia menjadi simbol perlawanan perempuan Toto.
Nasib tak baik juga menimpa para pejuang yang lain. Para pejuang pentolan seperti Datja Dhosa (Watu Api), Deru Gore (Kamubheka) , Rubu Radja (Tiwe) dan Sato Djoto (Kaburea) kemudian tertangkap dan dipenjarakan.
Darah ‘kepahlawanan’ Kepa Biu dan Ine No.’o kemudian mengalir deras dalam tubuh putra mereka, Aloysius Do Kepa, yang ketika rema belajar di OVO, Ndona. Beberapa tahun kemudian, Do Kepa pun mengoarkan api perlawanan kepada Hindia-Belanda dan menunutut semua Toto yang ditahan, dibebaskan.
Namun, karena perlawanannya itu, Do Kepa pun ditangkap lalu di buang ke Jawa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia dibuang ke Kalidonea Baru, negeri jajahan Belanda juga.
Itu baru nama-nama dari para pejuang dan tua adatnya sempat direkam dalam ingatan. Belum terhitung kematian dari warga yang setia di medan peperangan itu.
Jadi, tidak berlebihan kalau dikatakan tak ada wilayah di Flores, kecuali di Tanah Toto, yang jumlah mosalaki dan rakyat jelatanya, paling banyak meraih korban nyawa dan harta karena melawan pemerintah Hindia-Belanda.
Yang mengagumkan, perlawanan Kunu Toto menggugah beberapa suku-suku tetangga untuk memberikan bala bantuan.
Dikisahkan, selama perang berlangsung dari barat datang bantuan pasukan dari Suku Lambo di bawah komando Dhedhu Wati, juga pasukan dari Suku Dhawe dibawa pimpinan Rae Sape.
Mereka pun berjuang dengan gagah berani, hingga gugur di medan juang. Darah mereka menyatu dengan tanah Toto yang mereka bela.
Malasera, Simbol Kecerdikan Pejuang Toto
Perlawanan Kunu Toto memang tidak hanya rapi terkoordinasi, tetapi juga penuh taktik yang cerdik dan lihai.
Salah satu ‘simbol’ kecerdikan itu ada di Malasera (Madasela, menurut dialek Toto-Ute).
Menurut sejarawan P.H. Doko, di Kampung Malasera -kini berada di wilayah Desa Nata Ute, Kecamatan Nangaroro, telah terjadi momen paling dramatis dalam Perang Watuapi.
Betapa tidak, para serdadu Hindia-Belanda yang bergerak dari markasnya di Nangapanda di pantai selatan, melakukan pergerakan menyusuri aliran sungai Nangamboa, menuju ke utara, ke Wolowae.
Pergerakan mereka tertahan di Dia Bhui dan Madawitu karena dijegal oleh pasukan Kepa Biu.
Saat bergerak mundur, atas instruksi Kepa Biu, Wani Ghode berpura-pura bersikap ramah dan mengajak para serdadu itu singgah dan bermalam di Malasera.
Warga Kampung Malasera, segera menyediakan makanan dan minuman untuk para ‘tamu’ itu. Bahkan, mereka sengaja menyuguhkan ‘tuak terbaik’.
Merasa disambut baik, para serdadu itu melepaskan senjatanya dan menyantap semua suguhan dengan lahap.
Sementara itu, dalam kegelapan malam , Kepa Biu bersama pasukannya, sudah siaga. Mereka mengendap-endap di balik semak di sekitar Kampung Malasera, menunggu momen yang tepat untuk melakukan penyerbuan.
Ketika ‘para tamu’ itu mulai terlena karena mabuk dan rasa kantuk, pejuang Toto keluar dari balik-semak lalu membantai tanpa kenal ampun. Para sedadu itu kocar-kacir. Sebagian berhasil kabur, melarikan diri ke arah selatan, menuju Nangamboa dan seterusnya kembali ke markasnya di Nangapanda.
Namun, sebagian besar, sekitar 200 orang tewas di tempat. Mereka kemudian dimakamkan secara massal, di pinggiran Kampung Malasera. Makam massal itu, kini ditandai dengan tumpukan batu. (Lihat foto).

Memori Kolektif : Tercatat dalam Narasi Hati
Kisah perjuangan Kunu Toto tidak saja menjadi peristiwa sejarah masa lampau, tetapi menjadi narasi hati yang selalu ‘dilantunkan’ dan menginspirasi generasi muda Toto hingga saat ini.
Derita fisik dan luka bathin akibat kekejaman pemerintah Hindia-Belanda dan para serdadunya, oleh para pujangga Toto digubah menjadi syair adat (Baka Tjenda).
Narasi hati terkait perlawanan Kunu Toto tampak dalam Baka Tjenda dalam dialek Toto-Tenda Rea sebagai berikut:
• Buu bholo moo, jomba tungga mbonggo// Kami bekerja hanya untuk lelah, Menanggung letih yang tak berujung,
• Epu ghédu tana, 'angi wéo wolo // Gempa mengguncang dasar bumi, Angin menderu, mengoyak bukit-bukit.
• Tua roka 'opa, 'ata dii dhé o// Orang asing datang, hendak memungut pajak
• Epa ladé ghédu tolo wolo wéo // Polisi datang, menangkap kami, Kami gemetar, ketakutan dan terombang-ombang, tak tahu bersembunyi di mana
• Wéo kédi Déa ,'ura kita ngéra // Puncak gunung Déa berguncang, Otot kami terkoyak, jiwa kami remuk redam
• Sué wesa woku, wéa mérhé réra// Gading panjang kita terbuang, Emas berkarat kita pun lepas tercampak
• Kita panggu pata, bholo sudu pédé // Kita hanya bisa bernarasi, sekadar bercerita (tentang)
• Réra wéa mérhé, réra émbé dimba // Emas berkarat yang telah terbuang/terjual, hilang untuk selamanya
• Dau sa'o sina // Di toko orang/pedagang Cina/Tionghoa
• Bhaka sa tana, mona mé'a kita // (Kisah pilu seperti ini) terjadi di seluruh negeri, tidak hanya menimpa kita
• Réra suku bhala, mona wedi 'apa // Semua harta yang dijual hanya dibayar dengan koin perak, tak bernilai sama sekali
• Mona mé'a kita, rhembu sa tana // (Memang) kisah pilu ini tidak hanya menimpa kita, tetapi (terjadi) di seluruh negeri.
• Mbéo peka minggu, maé peka pedho // Ketika tiba saatnya, tidak ada yang mengi-ngira
• 'Iné weta wongé, 'amé nala ndero // (Saat) Kaum wanita bersukacita, kaum pria bergirang
• Datju nuka nanga, kapa nu mai // (Tampak) tiang kapal (bergerak) ke arah muara, kapal uap tiba,
• Wua 'ata laki,'ata fai pisu kasi // Hendak mengangkut para (pejuang) laki-laki, kamu wanita hanya merintih sedih.
Dalam bait-baitnya, syair ini menuturkan kisah getir Kunu Toto—sebuah tanah yang dipaksa memikul derita di bawah bayang penjajahan Hindia-Belanda. Keringat mereka diperas lewat kerja paksa, harta mereka dirampas lewat pajak dan penindasan, sedangkan rasa takut merayap di setiap sudut kampung.
Setiap larik adalah keluh kesah yang lahir dari hati rakyat, jeritan sunyi yang menembus waktu, menyingkap perlakuan semena-mena penguasa kolonial terhadap anak negeri.
Dalam situasi ini, Nipa Do, pemimpin suku Toto, tampil sebagai penopang harapan, menggerakkan rakyatnya untuk bertahan, menjaga martabat, dan menantang tirani yang mengekang kebebasan mereka.***
Sumber:
• Abraham Runga Mali: Ketika 'Babho' Tak Lagi Bertuah (bagian …). NagekeoPos (blog). (2015, Januari 2015). Diakses dari https://nagekeopos.blogspot.com/2015/01/abraham-runga-mali-ketika-babho-tak.html nagekeopos.blogspot.com
• Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979: “Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur”. Jakarta: 1984.
• Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). Sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Nusa Tenggara Timur. Jakarta: 1984.
• De Bruyne, W. J. (1947). Bestuursgeschiedenis van Flores [Monograf kolonial Hindia-Belanda].
• Residentie Timor en Onderafdeelingen. (n.d.). Bestuursverslagen [Laporan tahunan pemerintahan kolonial Belanda]. Den Haag: Nationaal Archief.
• NN. History of Flores, (trilingual: Belanda, Inggris, dan Indonesia) dalam https://flobamora.tripod.com/history.htm
• Perajaka, M. A. Menelusuri 'Jejak Majapahit' di Bumi Flores: Dari 'Nama', 'Gong Hujan', hingga 'Lesu' dan 'Bendera Majapahit, Merah Putih'. Floresku.com. (2025, 6 Februari). Diakses dari https://floresku.com/read/menelusuri-jejak-majapahit-di-bumi-flores-dari-nama-gong-hujan-hingga-lesu-dan-bendera-majapahit-merah-putih
• Primus Dorimulu: Kunu Toto, Nipado, Do Kepa, dan Sumpah Pemuda. Floresku.com. (2021, 22 Oktober). Diakses dari https://floresku.com/read/kunu-toto-nipado-do-kepa-dan-sumpah-pemuda ([turn0search0])
• Stefan Dietrich , Kolonialismus und Mission auf Flores ( ca. 1900-1942 ) , Hohenschäftlarn : Klaus Renner Verlag [ Münchner Beiträge zur Süd- und Südostasienkunde Band 1, 1989. ***