'Para Penjaga Tanah Kelimado' dalam Catatan Louis Fontijne, Potret Tua Kehidupan Orang Nage yang Dipajang Kembali oleh Gregory Forth
redaksi - Selasa, 01 Juli 2025 11:21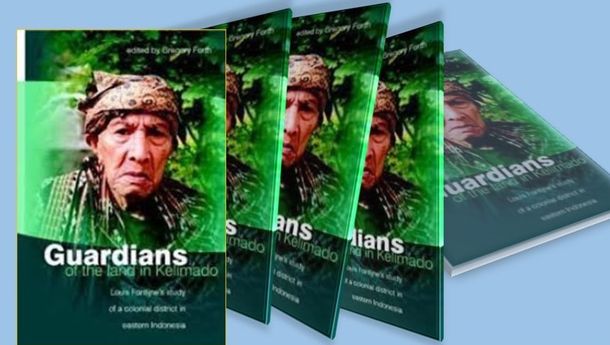 Buku 'Guardians Of The Land In Kelimado -Louis Fontijne's Study of a Colonial District in Eastern Indonesia' (sumber: Istimewa)
Buku 'Guardians Of The Land In Kelimado -Louis Fontijne's Study of a Colonial District in Eastern Indonesia' (sumber: Istimewa)- Judul: Guardians Of The Land In Kelimado -Louis Fontijne's Study of a Colonial District in Eastern Indonesia
- Pengarang: Gregory Forth
- ISBN : 9067182233
- Penerbit: Leiden : KITLV Press.
- Bahasa : English
- Halaman : 280
- Harga Resmi : Rp. 375.000

SIAPA yang belum dengar nama Gregory L. Forth? Forth ‘adalah orang Kanada, tetapi layak disebut sebagai ’orang Nagekeo' karena melalui berbagai penelitiannya ia tahu banyak tentang Nage dan Keo.
Di dunia akademis ia dikenal sebagai antropolog sosial terkemuka dan profesor emeritus di University of Alberta, tempat ia mengajar selama lebih dari tiga dekade sejak 1986.
Meraih gelar PhD dari Universitas Oxford pada 1980, Forth dikenal sebagai ilmuwan strukturalis dan interpretivis yang berkontribusi dalam bidang etnosains.
Ia telah menulis sejumlah buku tentang Indonesia Timur, dan sedikitnya dua buku penting yang khusus membahas budaya Nage, yaitu Beneath the Volcano: Religion, Cosmology and Spirit Classification Among the Nage of Eastern Indonesia dan Nage Birds: Classification and Symbolism Among an Eastern Indonesian People.
Dalam karya-karya ini, Forth menggali sistem kepercayaan, klasifikasi roh, simbolisme burung, serta kosmologi masyarakat Nage.
Selain buku, Forth juga menulis lebih dari seratus artikel ilmiah, dengan banyak di antaranya membahas struktur sosial, praktik budaya, dan sistem nilai masyarakat Nage. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Dualism and Hierarchy, yang juga menyinggung masyarakat Keo.
Bukunya ‘A Dog Pissing at the Edge of a Path’ yang membahas tentang bahasa 'metafora' dalam masyarakat Nage, terbit tahun 2019, memenangkan penghargaan untuk judul paling unik tahun 2020.
Pada 2023, ia mengusulkan kemungkinan Homo floresiensis masih hidup, berdasarkan kisah rakyat lokal seperti Ebu Gogo atau lpun Lai Ho’a.
BUKU, 'Guardians Of The Land In Kelimado -Louis Fontijne's Study of a Colonial District in Eastern Indonesia' ibarat ‘foto repro’ tentang kehidupan para penjaga tanah di Kelimado, selama paruh pertama abad ke-20.
Betapa tidak, melalui buku ini, Gregory Forth ‘memotret ulang’, sebuah ‘potret tua’ alias manuskrip perihal kehidupan para penjaga tanah Kelimado yang ditulis tahun 1940 oleh seorang pegawai kolonial Belanda bernama Louis Fontijne (1902–1968).
Konon, atas penugasan pemerintah kolonial Hindia Belanda, Fontijne melakukan penelitian mendalam mengenai sistem kepemilikan tanah adat dan kepemimpinan lokal di wilayah Residentie Timor en Onderhoorigheden, khususnya di daerah Kelimado, yang merupakan bagian dari distrik Nage di Flores Tengah.
Hasil dari penyelidikan ini membuahkan karya yang monumental: Grondvoogden in Kelimado — yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai Penjaga Tanah di Kelimado.
Meskipun disusun dalam konteks administratif dan birokratis kolonial, karya Fontijne jauh melampaui batasan laporan resmi pemerintah.
Dengan gaya dan pendekatan yang lebih menyerupai tesis akademik ketimbang laporan administratif, Fontijne menyuguhkan potret etnografi yang sangat kaya, detail, dan kritis mengenai masyarakat Nage, khususnya bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan budaya mereka mengalami perubahan sebagai akibat langsung dari lebih dari tiga dekade pemerintahan kolonial Belanda dan misi penginjilan Kristen.
Kelimado: Lokus Etnografi dan Simbol Keutuhan Nage
Wilayah Kelimado yang menjadi fokus penelitian Fontijne merupakan bagian sentral dari dunia Nage.
Dalam karyanya, ia menggambarkan Kelimado bukan sekadar sebagai unit administratif, tetapi sebagai ruang hidup yang sarat akan sistem nilai, simbolisme sosial, dan struktur kekuasaan yang kompleks.
Di sinilah ia menyaksikan bagaimana adat istiadat lokal yang kuat bersinggungan dan bahkan seringkali berbenturan dengan kebijakan kolonial serta intervensi misi Kristen yang mengubah tatanan nilai tradisional masyarakat.
Fontijne memperlihatkan bagaimana masyarakat Nage mengorganisasikan diri dalam struktur sosial yang ketat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kekerabatan, warisan tanah, dan otoritas adat.
Posisi kepala tanah — grondvoogd — memegang peran sentral dalam tata kelola masyarakat. Tanah tidak hanya dianggap sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai warisan spiritual dan identitas komunal yang sakral.
Warisan Sosial dan Dualisme Kekuasaan
Melalui pengamatan yang mendalam, Fontijne mengurai dinamika kekuasaan di antara para kepala tanah tradisional dan para pejabat kolonial yang ditunjuk.
Ia mencatat adanya ketegangan antara sistem otoritas adat dengan struktur pemerintahan kolonial, terutama ketika otoritas kolonial berupaya menghapus atau meminggirkan struktur kekuasaan lokal yang tidak sejalan dengan kepentingan administrasi kolonial.
Salah satu pengamatan tajam Fontijne adalah bagaimana kekuasaan kolonial secara sistematis menggantikan struktur sosial yang berbasis kekerabatan dan spiritualitas dengan sistem administratif rasional-legal ala Eropa.
Ia tidak hanya mencatat dampak negatif dari perubahan ini, tetapi juga mengkritik secara langsung kebijakan kolonial yang mengabaikan kompleksitas lokal dalam perumusan hukum dan pengelolaan tanah.
Fontijne mencatat bahwa kolonialisme secara tidak langsung telah menciptakan dualisme otoritas di Kelimado. Di satu sisi, masyarakat masih memegang teguh pada hukum adat dan otoritas tradisional. Di sisi lain, mereka dipaksa tunduk pada sistem pemerintahan kolonial yang menempatkan pejabat luar sebagai pengambil keputusan akhir.
Misi Kristen dan Erosi Budaya
Fontijne juga mengulas bagaimana pengaruh misi Kristen membawa perubahan besar terhadap kosmologi dan praktik-praktik spiritual masyarakat Nage. Ia menyaksikan bagaimana gereja berupaya menggantikan ritus-ritus tradisional dengan liturgi Kristen, serta mengarahkan pandangan dunia masyarakat dari animisme dan politeisme lokal ke monoteisme Barat.
Namun yang lebih menarik adalah bagaimana masyarakat Nage tidak serta-merta menggantikan kepercayaan lama mereka. Sebaliknya, Fontijne mencatat adanya sinkretisme — perpaduan antara kepercayaan lama dan ajaran Kristen — yang membentuk semacam “jalan tengah” dalam spiritualitas masyarakat. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa meskipun kolonialisme dan agama asing datang membawa kekuatan hegemonik, budaya lokal tetap menunjukkan daya tahan dan daya adaptasi yang tinggi.
Kritik Terhadap Kolonialisme
Yang membuat karya Grondvoogden in Kelimado sangat menonjol adalah keberanian Fontijne dalam mengkritik sistem kolonial itu sendiri. Ia tidak segan menyampaikan bahwa pendekatan kolonial sering kali tidak sensitif terhadap keragaman budaya dan struktur lokal, dan justru menimbulkan disorientasi serta ketimpangan sosial.
Bagi Fontijne, administrasi yang efektif seharusnya dibangun atas dasar pemahaman yang mendalam terhadap masyarakat lokal, bukan dengan memaksakan hukum dan sistem sosial Eropa atas masyarakat yang telah memiliki sistem sendiri selama ratusan tahun.
Melalui analisanya, Fontijne tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai penyampai suara masyarakat lokal yang selama ini dibungkam oleh narasi besar kolonialisme. Dalam konteks ini, ia termasuk dalam kelompok langka birokrat kolonial yang mampu melampaui perspektif “tuan dan bawahan” dan mencoba memahami dunia lokal dari sudut pandang internal.
Apresiasi Akademik oleh Gregory Forth
Lebih dari setengah abad setelah tulisan ini dibuat, karya Fontijne kembali dihidupkan dan diberi konteks baru oleh Gregory Forth — seorang antropolog terkemuka yang telah lama mengkaji masyarakat Nage.
Dalam bukunya Guardians of the Land in Kelimado, Forth menyunting, menerjemahkan, dan mengevaluasi karya Fontijne, menjadikannya lebih mudah diakses oleh para sarjana masa kini.
Forth memuji karya ini sebagai satu-satunya deskripsi menyeluruh tentang masyarakat Nage selama masa kolonial. Ia menilai pendekatan Fontijne sangat bernilai karena tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif — sesuatu yang langka dalam tulisan kolonial pada masa itu.
Sebagai seorang akademisi yang telah menulis beberapa buku penting seperti Rindi (1981), Beneath the Volcano (1998), Dualism and Hierarchy (2001), dan Nage Birds, Forth melihat kesinambungan antara observasi Fontijne dengan penelitiannya sendiri yang menekankan simbolisme, dualisme sosial, dan organisasi kekerabatan dalam masyarakat Flores Timur.
Warisan Intelektual dan Relevansi Kini
Narasi tentang orang Nage dalam karya Fontijne dan interpretasi Forth tidak hanya menyajikan potret sejarah dan budaya masa lalu. Ia juga mengandung pesan-pesan yang sangat relevan bagi masa kini — terutama terkait dengan bagaimana kebijakan pembangunan dan pemerintahan modern seharusnya memperhitungkan keragaman budaya lokal sebagai modal sosial, bukan hambatan.
Masyarakat Nage, sebagaimana dilukiskan Fontijne, adalah komunitas dengan nilai-nilai kekerabatan yang kuat, sistem pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, dan spiritualitas yang menyatu dengan lanskap geografis mereka. Ketika nilai-nilai ini terabaikan dalam perencanaan pembangunan, maka yang muncul adalah krisis identitas, degradasi ekologis, dan ketimpangan sosial.
Maka dari itu, warisan pengetahuan yang ditinggalkan Fontijne dan diperkuat oleh Forth menjadi semacam “cermin kritis” bagi bangsa Indonesia — untuk melihat kembali bagaimana sejarah interaksi antara kekuasaan dan budaya membentuk realitas sosial saat ini, dan bagaimana pemahaman mendalam terhadap masyarakat lokal dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Penutup
Karya Louis Fontijne tentang orang Nage di Kelimado adalah potret luar biasa tentang bagaimana masyarakat adat Flores berhadapan dengan kolonialisme dan perubahan nilai. Ia bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga sumber refleksi bagi masa depan.
Bersama dengan kajian Gregory Forth, Grondvoogden in Kelimado menjadi dokumen penting tentang ketegangan, ketahanan, dan transformasi sosial dalam masyarakat Nage — warisan intelektual yang tak ternilai bagi antropologi Indonesia dan sejarah timur Indonesia. (map). ***

