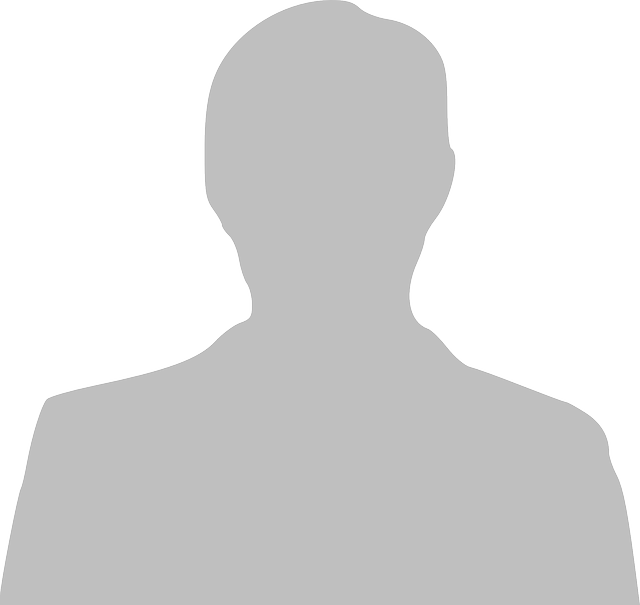Satu Peta Tak Cukup: Saatnya Indonesia Serius Mengintegrasikan 'Social-Cultural Mapping' ke dalam Tata Kelola Pembangunan
redaksi - Kamis, 07 Agustus 2025 13:46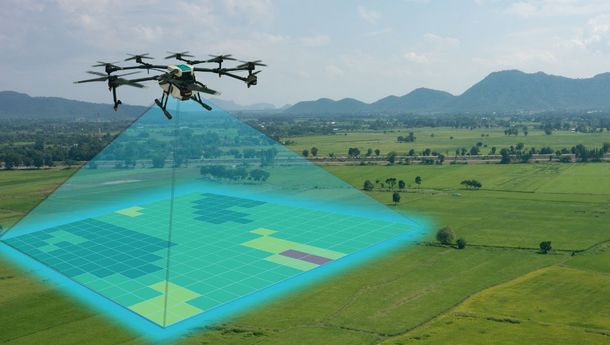 Ilustrasi: Proses pemetaan wilayah menggunakan teknologi drone. (sumber: Istimewa)
Ilustrasi: Proses pemetaan wilayah menggunakan teknologi drone. (sumber: Istimewa)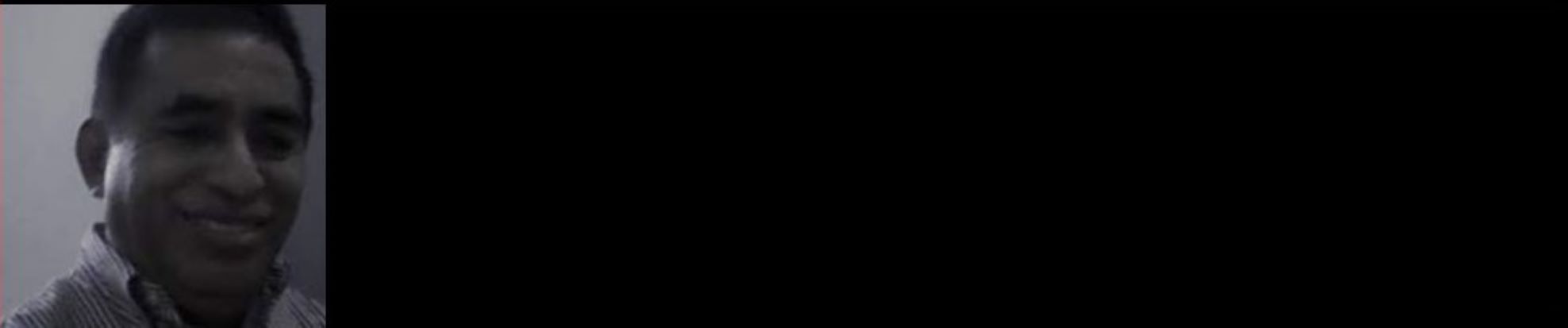
Oleh: Maximus Ali Perajaka*
MELALUI Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Pemerintah Indonesia melahirkan Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy (OMP).
Awalnya, KSP mencakup tiga kegiatan utama, yaitu kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi data geospasial. Namun, dengan diterbitkannya Perpres Nomor 23 Tahun 2021, ditambahkan satu kegiatan utama lagi, yakni berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Dengan demikian, hingga saat ini KSP mencakup empat kegiatan utama: kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta berbagi pakai data dan informasi geospasial.
Tujuan KSP jelas: mengatasi tumpang tindih data pertanahan, konflik wilayah, serta mempercepat pembangunan yang adil dan efisien. Dengan kata lain, melalui KSP, pemerintah ingin memastikan bahwa semua proses pembangunan—mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan sumber daya—berjalan berdasarkan satu peta yang sama.
Ruang lingkup KSP, tergolong sangat ambisius: mencakup 158 peta tematik dari 24 kementerian/lembaga dan 34 provinsi, meliputi aspek-aspek vital seperti perencanaan ruang, pertanahan, kehutanan, sumber daya alam, dan wilayah administrasi.
Melalui KSP, pemerintah ingin memastikan bahwa semua proses pembangunan—mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan sumber daya—berjalan berdasarkan satu peta yang sama.
Didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Bank Dunia, program ini tampak menjanjikan dan membawa angin segar bagi percepatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Namun, di balik KSP yang didukung oleh perangkat digital, satelit, dan teknologi GIS canggih, kita lupa satu hal yang sangat penting: manusia dan budaya.
Indonesia bukan sekadar gugusan pulau, melainkan ruang hidup yang dihuni oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis dengan nilai, relasi sosial, dan kearifan lokal yang tidak bisa dipetakan secara geografis semata.
Oleh karena itu, pertanyaan fundamental yang perlu kita ajukan hari ini adalah: Apakah Satu Peta cukup untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia? Jawaban kritisnya: tidak cukup.
Kita butuh Social-Cultural Mapping sebagai pelengkap dan penyeimbang dalam proses perencanaan pembangunan nasional.
Satu Peta: Canggih Secara Teknologi, Tapi Tumpul Secara Sosial
Tentu saja KSP mampu menghadirkan sistem informasi geospasial nasional yang dapat diandalkan karena diproses dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem informasi geospasial (GIS), penginderaan jauh (remote sensing), pemrosesan citra satelit resolusi tinggi, pemetaan menggunakan teknologi drone (drone mapping), cloud computing, big data analytics, serta platform geoportal untuk berbagi dan integrasi data spasial secara daring.
Produk KSP sangat bermanfaat untuk mengatasi tantangan kemajuan dan percepatan pembangunan. Selama ini banyak program pembangunan tersendat akibat konflik agraria dan tumpang tindih lahan yang justru bersumber dari perbedaan peta antara kementerian, atau bahkan antara pusat dan daerah.
Dalam konteks itu, KSP memang layak diapresiasi. Apalagi, sejak diuncurkan pada tahun, KSP telah mencatat berbagai kemajuan penting dalam upaya penataan dan integrasi informasi geospasial nasional.
Hingga Maret 2024, tercatat sebanyak 151 Peta Tematik atau Informasi Geospasial Tematik (IGT) telah berhasil disusun, dengan 141 peta di antaranya telah terintegrasi ke dalam sistem Geoportal Nasional.
Salah satu capaian signifikan adalah pengurangan tumpang tindih data pemanfaatan lahan yang berhasil ditekan hingga sekitar 19,97 juta hektare, dibandingkan kondisi pada tahun 2019.
Selain itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyelesaikan peta dasar berskala 1:50.000 dan kini tengah menyusun peta skala lebih rinci, yakni 1:5.000, guna mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengembangan kebijakan smart city di berbagai wilayah.
Meski begitu, capaian dalam penyusunan RDTR secara nasional masih terbatas: dari ribuan wilayah administrasi, baru terdapat 541 RDTR yang tersedia, dan hanya 278 RDTR yang telah terintegrasi ke dalam platform Online Single Submission (OSS).
Guna mempercepat proses perizinan dan tata kelola ruang yang lebih efisien, pemerintah menargetkan penyelesaian 2.000 RDTR baru dalam lima tahun mendatang, sebagai bagian dari agenda reformasi tata ruang nasional yang berbasis data spasial terintegrasi.
Namun di sisi lain, pendekatan ini masih terlalu fokus pada aspek fisik-spasial dan belum menyentuh dimensi sosial-budaya masyarakat.
KSP melihat tanah sebagai objek, bukan sebagai ruang hidup. Peta yang dihasilkan sebagian besar bersifat teknis: batas wilayah, kontur tanah, klasifikasi penggunaan lahan.
Padahal di balik garis-garis koordinat itu, terdapat komunitas hidup dengan sejarah, relasi sosial, nilai-nilai adat, dan kearifan lokal yang tak bisa direduksi hanya lewat warna dan layer dalam sistem GIS.
Singkatnya, kita berisiko menciptakan sistem pemetaan nasional yang akurat secara spasial, tapi tumpul secara sosial.
Pengabaian dimensi sosial-budaya dalam KSP berpotensi memicu konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat, kehilangan situs budaya, serta ketidaksesuaian pembangunan dengan kebutuhan lokal.
Akibatnya, pembangunan menjadi tidak inklusif, tidak berkelanjutan, dan menuai resistensi dari komunitas yang terdampak secara langsung.
Belajar dari Negara Lain: Peta Budaya dan Sosial Adalah Kunci
Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pembangunan yang mengabaikan konteks sosial-budaya berujung pada kegagalan jangka panjang.
Di Kanada, misalnya, proyek pembangunan infrastruktur skala besar di tanah-tanah adat suku First Nations sempat mengalami penolakan masif karena perencanaan dilakukan tanpa konsultasi budaya dan tanpa pemetaan nilai-nilai sosial masyarakat adat.
Hal serupa terjadi di Brasil, ketika pemerintah memaksakan pembukaan lahan pertanian di wilayah Amazon tanpa memahami struktur sosial masyarakat adat di sana.
Sebaliknya, di negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Finlandia, pemerintah telah mewajibkan socio-cultural impact assessment (penilaian dampak sosial-budaya) dalam setiap proyek pembangunan yang menyentuh wilayah masyarakat adat, termasuk pemetaan sosial dan budaya sebagai bagian dari sistem GIS nasional.
Hasilnya, konflik dapat ditekan, dan pembangunan berlangsung dengan penerimaan yang lebih kuat dari masyarakat lokal.
Mengapa ‘Socio-Cultural Mapping’ Penting?
Pertama, Peta Sosial-Budaya (Socio-Cultural Map) mampu menangkap aspek-aspek yang tidak terlihat dalam peta geospasial: jaringan relasi, struktur sosial, lembaga adat, persebaran kelompok rentan, akses terhadap layanan publik, hingga zona sakral dan larangan adat. Ini krusial dalam konteks pembangunan desa, wilayah adat, atau pemukiman informal di kota.
Kedua, pendekatan pemetaan partisipatif dalam social mapping memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan. Ketika masyarakat terlibat dalam memetakan desanya sendiri—rumah, kebun, sungai keramat, atau jalur evakuasi bencana—maka terbentuk sense of ownership yang kuat terhadap proses pembangunan.
Ketiga, integrasi data sosial-budaya dengan data spasial akan menciptakan informasi yang jauh lebih kaya dan kontekstual. Misalnya, jika geo-spatial map menunjukkan daerah dengan infrastruktur jalan buruk, dan peta sosial menunjukkan daerah yang dihuni oleh kelompok miskin dan minoritas etnis, maka intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Ironi: Negara Multikultur Tanpa Peta Budaya
Ironisnya, meski Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya tertinggi di dunia, namun kebijakan pemetaan nasional masih abai terhadap dimensi sosial-budaya.
Di banyak wilayah, proyek nasional seperti jalan tol, bendungan, atau kawasan industri dibangun tanpa pertimbangan terhadap kawasan sakral, situs sejarah lokal, atau zona larangan adat.
Contoh konkret dapat dilihat dalam beberapa kasus pembangunan di Papua dan Kalimantan, di mana komunitas lokal kehilangan akses terhadap lahan adatnya karena tidak pernah terdokumentasi secara resmi dalam sistem pemetaan pemerintah.
Ketika masyarakat adat menyatakan bahwa “di sana ada tanah kuburan leluhur,” namun peta resmi menyatakan “kosong”, maka yang berlaku adalah logika administrasi, bukan kearifan lokal.
Satu contoh konkret lain lagi adalah penolakan warga komunitas Poco Leok, Manggarai Flores atas proyek pembangunan perluasan energi panas bumi (geothermal).
Warga Poco Leok kuatir bahwa proyek geothermal iru berpotensi merusak lahan adat yang menjadi sumber penghidupan dan memiliki nilai sejarah serta spiritual. Pasalnya lahan adat tersebut meliputi hutan adat, kebun komunal (lingko), mata air (wae), ruang sosialisasi (natas labar), dan altar penyembahan (compang).
Integrasi: Jalan Menuju Peta Keadilan Sosial
Solusi terhadap ketimpangan ini bukanlah menolak teknologi geospasial, melainkan memperkaya dan melengkapinya. Integrasi antara geo-spatial maps dan social-cultural maps menjadi keniscayaan. Inilah yang disebut sebagai pendekatan spasial-holistik: melihat wilayah tidak hanya sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial dan simbolik.
Bank Dunia, sebagai mitra pembangunan Indonesia, seharusnya juga mendorong pendekatan ini dalam semua proyek yang mereka danai. Kementerian ATR/BPN dan Kemendagri, yang memimpin program Proyek Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang Terpadu atau Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), perlu berani menyusun Pedoman Pemetaan Sosial-Budaya Nasional yang terintegrasi dalam sistem GIS nasional pada KSP.
Prasyarat dan Tantangan
Namun, mengintegrasikan social-cultural mapping ke dalam sistem nasional bukan perkara mudah. Ada beberapa prasyarat yang mesti disiapkan:
Pertama, kerangka hukum dan kebijakan: Pemerintah perlu mengakui secara legal hasil pemetaan sosial-budaya sebagai dokumen perencanaan yang setara dengan peta geospasial teknis.
Kedua, SDM dan kapasitas daerah: Pemerintah daerah perlu diberi pelatihan dan sumber daya untuk menyelenggarakan pemetaan partisipatif bersama masyarakat.
Ketiga, keterbukaan data dan partisipasi: Peta bukan hanya milik teknokrat dan birokrat. Data harus terbuka, bisa diakses masyarakat, dan menjadi ruang dialog antara warga dan pemerintah.
Dan, keempat, koordinasi lintas sektor: Karena social-cultural mapping menyentuh banyak aspek—dari pendidikan, kesehatan, agama, hingga adat—maka dibutuhkan koordinasi antar kementerian dan lembaga secara menyeluruh.
Penutup: Menuju Peta Indonesia yang Lebih Adil
Jika pemerintah benar-benar ingin mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, maka integrasi geo-spatial map dan social-cultural map bukanlah pilihan, melainkan keharusan.
Satu Peta tanpa dimensi sosial-budaya adalah peta yang buta terhadap realitas masyarakat. Ia hanya akan mempercepat pembangunan fisik, tetapi memperlebar ketimpangan sosial.
Di tengah semangat reformasi agraria, digitalisasi layanan pertanahan, dan upaya desentralisasi perencanaan wilayah, mari kita tidak mengulangi kesalahan masa lalu: membangun jalan tapi memutus hubungan sosial, membuka lahan tapi mengabaikan sejarahnya, menyusun rencana tapi melupakan manusianya.
Satu Peta adalah langkah awal. Tapi Peta Sosial-Budaya adalah langkah penting berikutnya untuk membangun Indonesia yang benar-benar adil, manusiawi, dan kontekstual. *
*Maximus Ali Perajaka, adalah dosen, penulis dan peminat masalah sosial-budaya. ***