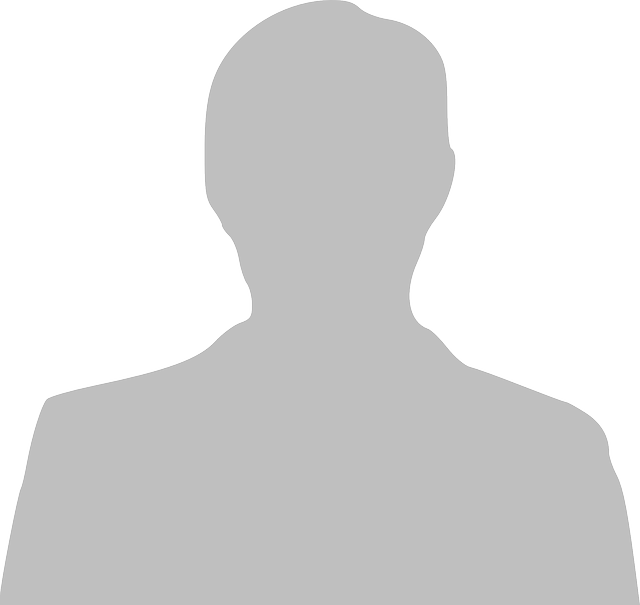SOROTAN: ‘Gelar Pahlawan’: Paradoks Soeharto dalam Ingatan Kolektif Bangsa Indonesia
redaksi - Minggu, 09 November 2025 12:55 (sumber: null)
(sumber: null)Oleh: Maxi Ali Perajaka*
KATA “pahlawan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai “orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran.”
Pahlawan adalah gelar bagi mereka yang dianggap berjasa besar bagi orang banyak dan berjuang demi kebenaran, kemerdekaan, serta kehormatan bangsa.
Dalam makna itu, siapa pun yang berkorban demi kebenaran dan kemaslahatan sesama sesungguhnya dapat disebut pahlawan.
Tetapi sebelum kata itu menjadi simbol nasionalisme dan kebanggaan, jejaknya jauh lebih tua, dan sarat makna spiritual serta budaya. Ia berakar dari bahasa, dari sejarah pertemuan peradaban, dan dari pergulatan manusia dalam menafsirkan apa arti keberanian sejati.
Jejak Bahasa dan Akar Makna
Kata "pahlawan" sepadan dengan kata bahasa Inggris ‘hero’. Kata ‘hero’ sendiri berasal dari bahasa Yunani ἥρως (hērōs), yang berarti pahlawan atau pejuang, khususnya seseorang yang memiliki keturunan dewa atau kemudian diberi kehormatan ilahi. Etimologi ini menunjukkan bahwa pahlawan adalah orang yang melindungi orang lain.
Dalam konteks Yunani kuno, sebutan ‘ἥρως (hērōs)’ merujuk pada sosok mitologis seperti Heracles yang memiliki sifat setengah dewa.Namun, di dunia modern, makna ini berkembang menjadi siapa pun yang menunjukkan keberanian luar biasa da an melakukan tindakan heroik, seperti menyelamatkan orang lain dari bahaya.
Secara etimologis, kata pahlawan memiliki beberapa kemungkinan asal-usul yang menarik. Salah satu pandangan menyebut kata ini berakar dari bahasa Sansakerta, gabungan antara kata phala yang berarti hasil atau buah, dan akhiran -wan yang berarti memiliki.
Maka, secara harfiah, pahlawan berarti “seseorang yang memiliki hasil” atau “yang berhak menerima buah (pahala)” atas tindakan dan perjuangannya.
Dalam pengertian ini, pahlawan adalah mereka yang pantas menerima phala — yakni pahala atau hasil suci — karena pengorbanan dan perjuangan mereka demi menegakkan kebenaran dan keadilan.
Dengan demikian, sejak awal, kata ini memuat unsur spiritual dan etis: seseorang tidak disebut pahlawan karena kekuatan semata, melainkan karena hasil perjuangannya melahirkan kebaikan bagi sesama.
- Terkuak Dugaan Kebobrokan di Desa Golo Ndari, Jabatan Fiktif, Dana Desa Gelap, dan Aparat Tak Pernah Kantor
- Rikardus Aman Tegaskan Telah Mundur dari Jabatan Kepala Dusun Baang Sejak 2021
- Dugaan Upaya Penculikan Siswi SDI Lowolabo, Polisi Lakukan Penyelidikan
Namun, pandangan lain menelusuri jejak kata pahlawan ke akar bahasa Persia, yakni pahlavān (پهلوان), yang berarti “orang gagah berani,” “pendekar,” atau “ksatria.”
Dalam tradisi Persia kuno, pahlavān bukan hanya pejuang di medan perang, tetapi juga simbol moralitas dan kehormatan. Ia adalah sosok yang menegakkan kebenaran, menolong yang lemah, dan mengendalikan diri dari keserakahan.
Kata ini tersebar luas ke dunia Melayu melalui jalur perdagangan dan penyebaran Islam sejak abad ke-13.
Dalam naskah-naskah klasik seperti Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Amir Hamzah, kata pahlawan digunakan untuk menyebut tokoh-tokoh yang gagah, setia, dan siap berkorban demi raja, agama, dan kebenaran. Dengan demikian, maknanya pun meluas: dari ksatria yang berani menjadi teladan kesetiaan dan kehormatan.
Dua Akar, Satu Semangat
Dari dua akar etimologis itu — Sansakerta dan Persia — lahirlah lapisan makna yang kaya. Dari Sansakerta, pahlawan mencerminkan nilai spiritual dan moral: seseorang yang berhak atas pahala karena berbuat mulia. Dari Persia, ia membawa jiwa kesatriaan dan keberanian: sosok yang membela kehormatan dan kemanusiaan.
Dua makna itu berpadu dalam sejarah dan budaya Indonesia, membentuk sosok pahlawan yang tidak hanya gagah dalam berperang, tetapi juga luhur dalam niat. Ia bukan sekadar pejuang dengan senjata, melainkan manusia yang berani menanggung risiko demi kebenaran.
Dari Ksatria ke Patriot
Dalam sejarah Indonesia modern, terutama sejak masa perjuangan kemerdekaan, makna pahlawan mengalami proses nasionalisasi. Ia bergeser dari konsep personal menuju simbol kolektif perjuangan bangsa.
Gelar ini tidak hanya disematkan kepada mereka yang gugur di medan perang, tetapi juga kepada siapa pun yang memberikan pengorbanan besar bagi kemerdekaan, kemanusiaan, dan kebenaran.
Semangatnya berakar pada keyakinan religius yang mendalam: hubb al-wathan min al-iman — “cinta tanah air adalah bagian dari iman.” Dalam pandangan ini, pahlawan adalah wujud konkret dari cinta yang bertanggung jawab: cinta yang diwujudkan dalam kerja, pengorbanan, dan keberanian moral.
Dengan demikian, kata pahlawan memuat tiga dimensi makna yang saling melengkapi:
Pertama, Spiritual-etimologis – dari akar kata phala-wan: yang berhak menerima pahala atas amal perjuangan.
Kedua, Kultural-historis – dari pengaruh Persia: sosok ksatria yang berani, jujur, dan terhormat.
Ketiga, Nasional-modern – sebagai simbol pengorbanan dan cinta tanah air demi kemerdekaan dan kemanusiaan.
Maka, menjadi pahlawan bukanlah soal gelar, melainkan soal keberanian untuk berbuat benar, membela sesama, dan mencintai negeri dengan sepenuh hati.
Siapakah sebenarnya pahlawan itu?
Pertanyaan ini tampak sederhana, namun jawabannya terus bergeser dari zaman ke zaman. Dalam dunia modern, batas antara pahlawan, pemimpin, dan panutan sering kali kabur.
Selebriti dan bintang olahraga, misalnya, kerap disanjung sebagai “pahlawan media” hanya karena popularitas dan pencapaiannya di depan kamera.
Di sisi lain, ketika bencana melanda, sosok-sosok yang menolong dan membangun kembali kehidupan disebut pahlawan kemanusiaan.
Para guru yang berdedikasi mendididik generasi muda, dan petugas kesehatan yang melayani pasien secara tulus tetapi mendapatkan ‘reward’ yang layak sering disebut sebagai ‘pahlawan tanpa tanda jasa’.
Bahkan dalam ruang pribadi, banyak orang menjadikan orang tua atau keluarga mereka sendiri sebagai pahlawan kehidupan.
Kepahlawanan, seperti dicatat para peneliti (Kinsella, Franco, Goethals, dan Zimbardo), tak hanya soal keberanian atau pengorbanan, melainkan juga tentang daya pengaruh terhadap perasaan, pikiran, dan tindakan orang lain.
Pahlawan sejati mampu menyalakan harapan, menumbuhkan semangat, dan mengingatkan manusia akan kebaikan dunia. Mereka menjadi cermin moral yang menginspirasi dan menggerakkan.
Survei global menunjukkan dua pertiga orang dewasa memiliki sosok pahlawan pribadi. Ini membuktikan bahwa kebutuhan akan figur pahlawan bersifat universal—ia hadir bukan hanya di panggung perang atau sejarah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di antara mereka yang dengan tulus berbuat baik tanpa mengharap sorotan.
Pertanyaan yang Mengusik: Apakah Soeharto Pantas Disebut Pahlawan Nasional?
Dari makna-makna luhur itu, muncul pertanyaan yang menggugah dan kontroversial:
Apakah Soeharto pantas disebut Pahlawan Nasional?
Pertanyaan ini bukan sekadar perdebatan politik atau wacana publik sesaat, melainkan uji moral dan historis bagi bangsa Indonesia dalam memahami arti kepahlawanan yang sejati.
Jika pahlawan adalah seseorang yang berjuang dengan gagah berani demi kebenaran, yang rela berkorban tanpa pamrih, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, maka menilai Soeharto tidak bisa dilakukan secara sederhana. Ia menuntut pandangan yang jujur dan seimbang — antara jasa besar dan bayang-bayang kontroversi.
Antara Jasa dan Luka
Tidak dapat disangkal, Soeharto memiliki jasa besar dalam membangun Indonesia pasca-1966. Ia memimpin masa transisi dari kekacauan politik menuju stabilitas ekonomi yang panjang. Melalui Orde Baru, Soeharto menata birokrasi, mengundang investasi asing, dan meluncurkan program pembangunan nasional yang terencana.
Program seperti Inpres Desa Tertinggal, transmigrasi, dan pembangunan infrastruktur dasar telah mengubah wajah Indonesia dari negara agraris menuju negara industri yang berkembang. Ia juga menorehkan prestasi monumental berupa swasembada pangan pada tahun 1984 — capaian yang menjadi simbol keberhasilan manajemen ekonomi nasional kala itu.
Bagi sebagian generasi, Soeharto dikenang sebagai “Bapak Pembangunan.” Ia dianggap telah meletakkan fondasi kemajuan ekonomi dan kestabilan politik selama lebih dari tiga dekade.
Namun, di sisi lain, sejarah tidak bisa menutup mata pada lembaran kelam pemerintahannya. Di bawah kekuasaan yang panjang, kebebasan berekspresi dibungkam, oposisi politik dibasmi, dan kritik dibungkus dengan ancaman.
Tragedi 1965–1966, penahanan tanpa pengadilan, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, Aceh, dan Papua menjadi noda yang tidak bisa dihapus begitu saja.
Selain itu, praktik korupsi sistemik dan kolusi keluarga Cendana menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang dalam. Kekayaan segelintir elit menumpuk di atas penderitaan rakyat kecil. Maka, meski pembangunan fisik melesat, keadilan sosial — yang menjadi cita-cita kemerdekaan — justru tertinggal jauh.
Antara Pahala dan Dosa
Dari perspektif etimologis dan moral, pahlawan adalah phala-wan — “mereka yang berhak atas pahala.” Pertanyaannya kini menjadi lebih tajam:
Apakah seseorang yang meninggalkan warisan pembangunan besar tetapi juga luka kemanusiaan dapat disebut pahlawan dalam arti penuh?
Penilaian atas kepahlawanan Soeharto menuntut kejujuran sejarah dan keseimbangan nurani.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap jasanya, tetapi juga tidak boleh mengabaikan penderitaan yang ditimbulkannya. Dalam pandangan banyak sejarawan, Soeharto adalah paradoks: pahlawan bagi sebagian, dan penguasa yang menindas bagi sebagian lainnya.
Menimbang Gelar, Menakar Nilai
Ketika wacana pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional muncul dari berbagai pihak, bangsa ini seolah dihadapkan pada cermin sejarahnya sendiri.
Apakah gelar “pahlawan” cukup diukur dari capaian pembangunan dan stabilitas politik, ataukah harus juga menimbang aspek moral, keadilan, dan kemanusiaan?
Sebagian pihak berargumen bahwa jasa Soeharto terhadap pembangunan nasional tak bisa dihapus hanya karena kesalahan politiknya.
Namun sebagian lainnya berpendapat: pahlawan sejati tidak hanya membangun gedung dan jalan, tetapi juga membangun keadilan, kebebasan, dan martabat manusia.
Maka, sebelum gelar “Pahlawan Nasional” disematkan, bangsa ini perlu menjawab pertanyaan moral yang mendasar:
Apakah kita menghargai keberhasilan yang dicapai dengan mengorbankan kebenaran,
atau kita menegakkan kebenaran meski harus menghadapi bayang-bayang kekuasaan yang pernah berjasa?
Makna Kepahlawanan yang Sejati
Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap bangsa memerlukan pahlawan, tetapi tidak semua yang berjasa pantas disebut pahlawan.
Pahlawan sejati adalah mereka yang berani melawan ketidakadilan, bukan yang menutupi kesalahan demi stabilitas. Mereka yang memperjuangkan kesejahteraan tanpa mengorbankan kebebasan. Mereka yang membela rakyat, bukan menaklukkan rakyatnya.
Dalam arti itu, menjadi pahlawan adalah perjalanan moral, bukan sekadar capaian politik. Ia lahir dari ketulusan, bukan dari kekuasaan. Ia bertahan bukan karena gelar, tetapi karena integritasnya diingat dalam nurani rakyat.
Hasil sejumlah studi ilmiah menegaskan, ‘pahlawan’ bermakna mewariskan nilai-nilai, menanamkan harapan, meningkatkan semangat dan persahabatan, membuatdunia menjadi tempat yang lebih baik, danmengingatkan orang-orang tentang ‘bonum commune’ (Kinsella, Ritchie, & Igou, 2015a).
Pahlawan juga dipandang sebagai teladan moral dan model perilaku yang mampu memotivasi individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik (Klapp, 1969).
Lebih dari itu, pahlawan berperan sebagai cermin sosial yang membantu orang memahami norma dan nilai dalam komunitasnya (Goethals & Allison, 2012; Cohen, 1993). Nilai-nilai kepahlawanan memberikan arah bagi individu untuk menemukan makna hidup dan membangun motivasi diri (Coughlan dkk., 2017).
Dalam konteks ini, pahlawan menjadi inspirasi bagi upaya manusia mencapai kehidupan bermakna dan abadi melalui tindakan yang memberi dampak bagi sesama.
Delapan ciri utama kepahlawanan meliputi: peduli, karismatik, inspiratif, terpercaya, tangguh, tanpa pamrih, pintar, dan kuat—suatu kombinasi sifat yang menjadikan mereka panutan moral dan simbol ideal bagi masyarakat.
Penutup
Etimologi dan sejarah kata pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa keberanian sejati tidak hanya diukur dari kemenangan, tetapi dari niat dan dampaknya bagi kemanusiaan.
Soeharto mungkin pahlawan bagi sebagian, tetapi pengingat bagi yang lain — bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan selalu melahirkan luka.
Akhirnya, mungkin bangsa ini perlu ‘merenung’ sebelum memutuskan apakah Soeharto layak disebut Pahlawan Nasional.
Namun, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa bangsa Indonesia belajar dari sejarahnya sendiri — agar di masa depan, gelar pahlawan benar-benar disematkan kepada mereka yang bukan hanya membangun negeri, tetapi juga memanusiakan bangsanya. (*)
*Pemimpin redaksi Floresku.com. ***