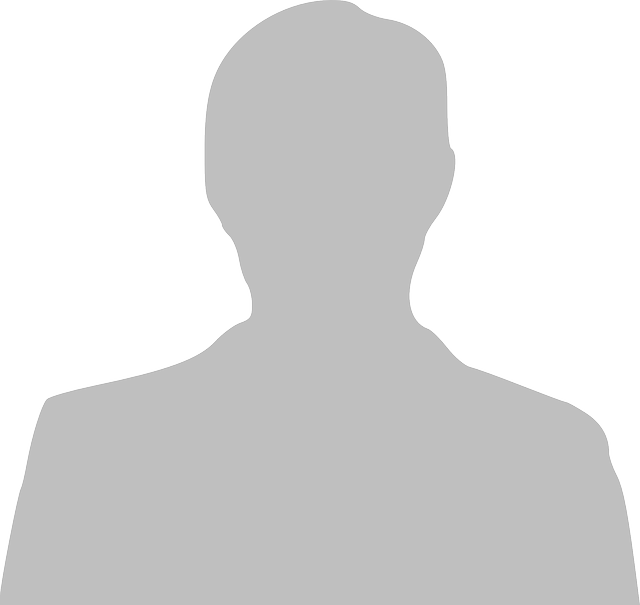Benang Waktu: Sejarah Panjang Tradisi Menenun di Flobamora
redaksi - Senin, 03 November 2025 14:11 The Broze Weaver -- patung perungguh dari sekitar abad ke-6 M menggambarkan seorang wanita dengan alat tenun sederhana. (sumber: artsandculture.google.com)
The Broze Weaver -- patung perungguh dari sekitar abad ke-6 M menggambarkan seorang wanita dengan alat tenun sederhana. (sumber: artsandculture.google.com)Oleh: Maxi Ali Perajaka*
Flobamora—Flores, Sumba, Timor, dan Alor—selalu dikenal sebagai gugusan pulau dengan tradisi menenun yang luar biasa. Di setiap lembah dan pesisirnya, benang-benang warna-warni menjadi cermin kehidupan, doa, dan kebanggaan perempuan.
Namun, di balik keindahan itu, terselip pertanyaan mendasar: sejak kapan orang Flobamora mulai mengenal tradisi menenun?
Apakah mereka belajar dari pedagang India pembawa kain Patola pada abad ke-16? Ataukah menenun sudah menjadi bagian dari warisan nenek moyang Austronesia yang jauh lebih tua —bahkan sebelum para saudagar ‘asing’ menjelajah kawasan Nuntaran bagian Timur?
Syair dan Ular Sawah: Jejak Lisan yang Tertua
Jejak tertua tentang menenun di Flores tidak datang dari arsip kolonial, melainkan dari syair-syair kuno masyarakat Sikka dan Lio, yang diwariskan secara lisan turun-temurun. Dalam syair orang Kowe Sikka yang ditulis Orin Bao (1969), terdapat bait puitik yang mencerminkan pandangan kuno terhadap keindahan kain:
“Kelang kirek lagar / Ganu Nagasawaria” (Ragam hias yang berwarna-warni / seperti kulit ular sawah besar).
Motif Nagasawaria bukan sekadar corak visual, tetapi perwujudan hubungan spiritual dengan leluhur. Ular bagi orang Sikka adalah simbol daya hidup dan pelindung.
Dengan meniru warna kulit ular dalam tenunan, perempuan penenun menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh.
Tradisi ini menunjukkan bahwa menenun berakar pada kosmologi animistik lokal, jauh sebelum perdagangan global membawa kain India, Arab, atau Eropa. Tenun adalah doa yang dijalin, bukan sekadar pakaian yang dikenakan.

Patola dan Diplomasi Benang
Sejarawan J.C. van Leur (1955) menggambarkan bahwa sejak abad ke-16, pesisir Nusantara Timur telah menjadi panggung perdagangan maritim internasional—antara Gujarat, Coromandel, Tiongkok, Portugis, dan Belanda.
Salah satu barang mewah paling diminati ialah Patola, kain sutra bermotif geometris hasil teknik tenun ganda dari India Barat.
VOC mencatat bahwa kain Patola digunakan sebagai alat diplomasi dan simbol status.
Para raja di Flores, Sumba, Sabu, Timor hingga lembata dan Alor hingga Flores menukar cendana, lilin, bahkan budak dengan selembar kain India. Kain bukan sekadar benda: ia adalah lambang kekuasaan dan jembatan hubungan sosial.
Bahkan dalam mitologi lokal, kisah asal-usul raja sering menyinggung kain sebagai simbol keagungan. Artinya, pengaruh Patola bukan hanya estetis, tetapi juga spiritual—ia merasuk ke dalam imajinasi dan identitas.
Antara Ketelanjangan dan Kehormatan
Namun paradoks muncul. Jika tradisi menenun sudah dikenal sejak era Austronesia—yakni 4.000–5.000 tahun lalu—mengapa catatan misionaris dan pegawai VOC abad ke-16–17 menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk di kawasan Flobamora masih berpakaian minim?
Sebuah laporan misionaris Katolik di Timor tahun 1670 mencatat dengan nada heran: “Pakaian perempuan terbatas hanya pada tato di tubuh—seperti orang Moor di Afrika—dari pergelangan kaki sampai lutut seperti sepatu bot, dari jari tangan hingga siku, dan di seluruh bahu.” (Teixeira, 1957, hlm. 452).
Namun kesaksian ini tentu perlu dibaca kritis. “Ketelanjangan” dalam pandangan misionaris bukan berarti tanpa pakaian, melainkan tidak sesuai dengan peraturan moral Barat.
Banyak komunitas Austronesia Timur mengenakan cawat dari kulit kayu atau kain pinggang sederhana—pakaian yang fungsional dan sarat simbol.
Dalam catatan yang sama, misionaris menambahkan bahwa perempuan elite mengenakan dua kain, disebut Costal—kemungkinan berasal dari kata coastal, menunjuk pada barang pesisir India atau Coromandel.
“Satu kain menjuntai dari pinggang ke bawah, satu lagi disampirkan di bahu. Mereka juga memakai gelang gading di kedua lengan—itulah pakaian pesta mereka.” (Teixeira, 1957, hlm. 452).
Dari sini tampak bahwa kain—terutama kain impor—menjadi penanda status sosial.
Hanya kalangan bangsawan yang dapat memilikinya, sementara rakyat biasa mengenakan pakaian minimalis dari serat lokal. Dengan demikian, menenun belum menjadi budaya massal, melainkan ritual simbolik di lingkaran terbatas.
Kain Sebagai Bahasa Roh
Dalam konteks itu, tradisi menenun di Flobamora mungkin tidak lahir dari kebutuhan berpakaian, tetapi dari kebutuhan spiritual.
Kain adalah bahasa sakral untuk berbicara dengan leluhur. Hingga kini pun, sebagian besar kain ikat tidak dikenakan setiap hari, melainkan hanya dalam upacara: pernikahan, kematian, atau persembahan adat.
Antropolog Gregory Forth (1998) mencatat bahwa dalam masyarakat Lio, kain bukan benda mati, melainkan “entitas berjiwa” yang terlibat dalam hubungan manusia dan roh. Maka, menenun adalah ritual komunikasi, bukan sekadar kerajinan rumah tangga.
Bukti Arkeologis: Sang Penenun Perunggu
Temuan arkeologis mendukung pandangan bahwa tradisi menenun di Flobamora sudah sangat tua.
Di situs Melolo (Sumba Timur), arkeolog menemukan berbagai benda prasejarah terkait menenun, seperti tenunan perangko, alat pemintal, serta kain berbahan katun yang berusia lebih dari 3.000 tahun.
Selain itu, juga ditemukan batu pemukul yang berfungsi untuk mengolah kulit kayu menjadi kain (Kuswara, 2022).
Sementara itu, di sebuah desa di Flores ditemukan sebuah patung perunggu abad keenam yang diberi nama ‘The Broze Weaver’.
Patung ini menggambarkan seorang penenun yang duduk di alat tenun sederhana, mengenakan kain sebatas betis, berambut dikepang, dan memakai anting besar berongga
Patung ini merupakan salah satu karya seni Asia Tenggara tertua dan paling berharga dalam koleksi National Gallery of Australia. Berdasarkan penanggalan inti tanah liatnya, patung ini dibuat antara tahun 556 hingga 596 Masehi.
Karya ini jelas mencerminkan gaya arkais Asia Tenggara yang terkait dengan kepercayaan animisme sebelum pengaruh Hindu–Buddha masuk ke wilayah tersebut.
Bukti-bukti arkeologis tersebut menunjukkan bahwa jauh sebelum datangnya pedagang Gujarat, India, Tiongkok Portugis dan VOC, perempuan di Flores sudah menenun kain sendiri,
Hal ini mempertegaskan keyakinan bahwa menenun adalah bagian dari jati diri peradaban Austronesia Timur.
Jaringan Dagang dan Transformasi Estetika
Kedatangan Patola India pada abad ke-16 memperluas cakrawala estetika di kawasan Nusantara bagian timur, termasuk Flobamora.
Sebuah teks yang ditulis pada tahun 1544 menyebukan, hingga pertengahan abad ke-16 kain tenun Patola dari India telah ramai diperdagangkan di wilayah Nusantara timur.
Teks tersebut dengan kesaksian Santo Fransiskus Xaverius. Dikatakan, pada September 1545, Fransiskus Xaverius menumpangi kapal dari Gowa, India menuju Malaka.
Dalam catatannya, ia menyebutkan bahwa kapal Koromandel memuat sekitar 600 bal kain tenun berbahan kapas dari Pantai Koromandel. Kain-kain ini sangat bernilai bagi masyarakat Melayu.
Satu bal berisi sekitar 120 lembar kain, dengan total nilai mencapai 80.000 cruzado. Barang tersebut mencakup kain putih dari Masulipatam, Kaleture, dan Armogan, serta kain berwarna cerah berpola dari Sao Thomd, Nega-patam, dan Kanyimedu (jesuit-online-library.bc.edu).
Para sejarawan mencatat bahwa pada awal abad ke-17, impor kain India melonjak tajam: lebih dari 400.000 potong masuk ke Maluku dan daerah sekitarnya, hanya dalam satu tahun.
Saat itu terbentuk perdagangan segitiga: logam mulia dari Tiongkok dan Jepang ditukar oleh pedagang Eropa untuk membeli tekstil India, yang kemudian dibarter dengan rempah-rempah di Kepulauan Maluku (Barrkman, 2006).
Kain berkilau itu menjadi model kemewahan dan inspirasi desain baru. Sementara bahan katun impor membuka peluang tekstur baru di tangan perempuan lokal.
Catatan VOC (1335, 1678) bahkan menyebut bahwa orang Ende membawa benang katun ke Sumba untuk ditukar dengan sarung hasil tenunan Sumba—sebuah indikasi jaringan dagang intra-pulau yang dinamis.
Pada abad ke-18, Gubernur Portugis di Lifau menulis bahwa orang Timor “memproduksi kain halus dari kapas mereka sendiri”—menandakan lahirnya ekonomi tekstil lokal yang mandiri, berakar pada keterampilan perempuan (Teixeira, 1957).
Namun transformasi ini berjalan perlahan. Pengaruh India membawa teknik pewarnaan alami—nila biru, akar merah, dan simetri motif—tetapi perempuan Flobamora menafsirkan ulang dengan simbol-simbol lokal: ular, burung, matahari, dan motif kosmos.
Dari sinilah lahir ratusan motif khas Flores, Lio, dan Timor yang kita kenal hari ini—hasil perkawinan antara estetika India dan spiritualitas Austronesia.
Dari Kolonialisme ke Resistensi Budaya
Dalam konteks kolonialisme, menenun menjadi bentuk perlawanan simbolik. Sementara misionaris Eropa memandang tubuh tropis dengan kacamata moral dan “ketelanjangan”, masyarakat lokal menegaskan identitasnya lewat kain adat.
Setiap motif menjadi narasi tentang leluhur dan kosmos. Dalam masyarakat adat Sikka, perempuan yang mampu menenun disebut “ina ledo”—perempuan yang telah mencapai kedewasaan spiritual, karena mampu menganyam masa lalu dan masa kini.
Bagi perempuan Flobamora, menenun adalah tugas suci dan politik tubuh: tubuh yang dipandang rendah oleh kolonialisme justru menjadi sumber penciptaan nilai. Dalam tiap helai kain, mereka menulis ulang sejarah dalam bentuk visual, tanpa huruf dan tinta.
Bahasa Tanpa Huruf
Antropolog Barnes (2015) menyebut bahwa menenun di Indonesia Timur adalah a complex semiotic system—sistem tanda yang mengandung identitas, struktur sosial, dan sejarah migrasi. Setiap simpul benang merekam perjalanan komunitas, pernikahan antar suku, bahkan jalur perdagangan kuno.
Dengan demikian, orang Flobamora bukan sekadar penerima pengaruh luar, melainkan pencipta bahasa budaya sendiri. Kain ikat mereka menjadi teks visual yang hidup, setara dengan manuskrip peradaban lain.
Di tangan perempuan, kain menjadi arsip ingatan kolektif—menyimpan kisah tentang laut dan gunung, perdagangan dan cinta, perang dan perdamaian.
Seperti kata pepatah Sikka: “Watu lela, wiwi mitan”—batu tetap, benang bersambung. Artinya, dunia berubah, tapi tenun tetap mengikat jiwa komunitas.
Dari Kapas ke Identitas
Kini, di tengah gempuran mesin dan mode global, tradisi menenun di Flobamora tetap hidup. Ia menolak menjadi “folklor mati”, karena terus beradaptasi. Di Ende, Maumere, dan Insana, motif lama ditafsirkan ulang oleh generasi muda sebagai busana kontemporer tanpa kehilangan makna sakralnya.
Namun pertanyaan historis itu tetap bergema: kapan sebenarnya orang Flobamora mulai menenun?
Jawabannya mungkin tidak tunggal. Sebagian motif lahir dari kosmologi Austronesia ribuan tahun lalu; sebagian lain dari inspirasi India dan perdagangan kolonial.
Tapi yang pasti, menenun telah menjadikan Flobamora bagian dari sejarah dunia—bukan sebagai pinggiran, melainkan pusat kreativitas di antara angin perdagangan dan ombak sejarah.
Kain Sebagai Sejarah yang Hidup
Tradisi menenun di Flobamora tumbuh dari lapisan sejarah panjang: akar Austronesia kuno, estetika India, moral kolonial, hingga ekspresi modern.
Menenun bukan sekadar pekerjaan rumah tangga, melainkan filsafat hidup dan sistem pengetahuan perempuan.
Setiap helai kain ikat adalah teks sejarah yang dijalin tangan manusia—tentang bagaimana masyarakat pulau-pulau ini memahami dunia, bernegosiasi dengan modernitas, dan menjaga kesucian hubungan dengan leluhur.
Tubuh boleh berubah, tetapi kain tetap menjadi saksi. Kain tenun adalah sejarah yang bisa disentuh, doa yang bisa dipakai, dan identitas yang terus dijalin ulang—benang demi benang, generasi demi generasi. (Dariberbagai sumber). *
*Maxi Ali Perajakan, penulis buku ‘Pesona Seni Tenun & Budaya Nagekeo’, Penerbit Nusa Indah (2023). ***