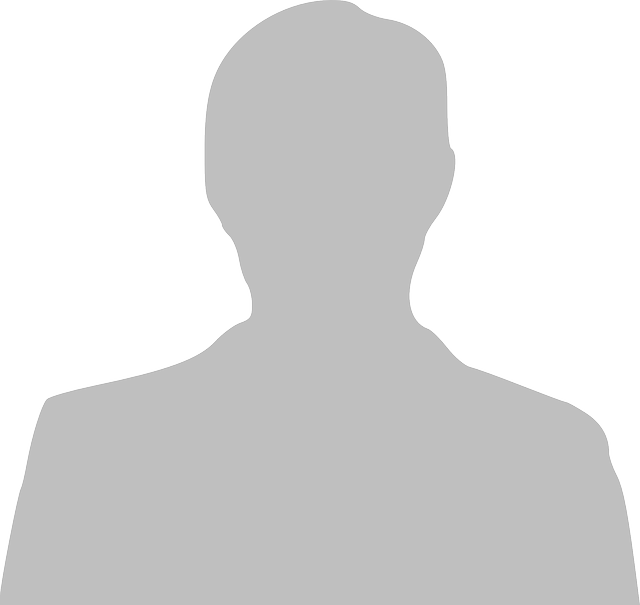SOROTAN: Penduduk Miskin NTT Berkurang, Yang Benar Saja...
redaksi - Sabtu, 15 Februari 2025 20:30 Potret orang miski di NTT (sumber: Istimewa)
Potret orang miski di NTT (sumber: Istimewa)Oleh: Maxi A. Perajaka
MENURUT data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2024 mencapai 5.656.039 orang.
Kemudian, pada 15 Januari 2025 lalu, BPS juga merilis data bahwa hingga September 2024, terdapat 1,11 juta orang, masih hidup di bawa garis kemiskinan.
Per definisisi, garis kemiskinan adalah jumlah minimum uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin dan mempertimbangkan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan
Secara rata-rata, garis Kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2024 adalah sebesar Rp3.031.831,-/bulan, naik sebesar 1,31 persen dibanding kondisi Maret 2023 yang sebesar Rp2.992.498-/bulan.
Kemiskinan, masalah yang terus bertambah
Kemiskinan aalah fenomena sosial ekonomi yang memiliki banyak dimensi dan kompleks. Karena sifatnya yang multidimensi, sulit untuk memberikan definisi yang tepat tentang kemiskinan dan orang miskin.
Kesadaran akan kemiskinan berkembang seiring dengan mitos filosofis tentang kemajuan. Selama abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17, jumlah orang miskin terus meningkat, dan setelah itu, jumlahnya terus bertambah.
Kemiskinan memiliki berbagai tingkat dan lapisan dengan intensitas dan dampak yang berbeda-beda pada manusia dan masyarakat.
Sejarah manusia hampir tidak memiliki contoh masyarakat yang sepenuhnya bebas dari kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya masalah negara, negara atau wilayah; tetapi juga masalah di seluruh dunia di mana masyarakat secara jelas terbagi antara yang kaya (atau tidak miskin) dan yang miskin.
Kata 'Miskin' (Inggris: poor’ berasal dari istilah Latin 'Pauper', yang dekat dengan Paucus dan Penes dan Penia: Ponos; dan Pione dalam bahasa Yunani.
Keadaan kemiskinan diungkapkan dengan kata Yunani aponia. Akar kata Yunani merujuk pada dua fakta positif: Satu adalah rasa lapar biologis; dan yang lainnya adalah rasa bingung atau malu secara psikologis.
Dengan demikian, kata Yunani memiliki konotasi kualitatif sedangkan akar kata Latin memiliki konotasi kuantitatif.
Ketika konsep miskin dan kaya dipandang dari sudut pandang etimologis, rasa lapar dan kekuasaan tampak tidak sepadan secara kualitatif, demikian pula kemiskinan dan kelimpahan juga berada pada garis yang sama.
Namun, pengayaan dan pemiskinan menggambarkan gerakan sepanjang garis tersebut ke arah yang berlawanan: keduanya tidak saling bertentangan tetapi hanya berlawanan.
Hal ini menjelaskan fakta bahwa keduanya bersifat relatif dan mungkin ada posisi perantara.
Kemiskinan dan kekayaan terkait dengan konteks fisik dan sosial ini, dengan sikap pribadi orang, dan dengan kebutuhan material dan budaya individu atau kelompok.
Meskipun kasus ekstrem mudah diidentifikasi, tidak mudah untuk melacak garis pemisah yang dapat diterima secara universal di antara keduanya.
Kemiskinan ekstrem terjadi di semua negara di dunia, terlepas dari situasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka dan secara serius mempengaruhi keluarga dan kelompok individu yang paling rentan dan kurang beruntung yang terhalang dalam menjalankan Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental mereka.
Sebagian besar manusia hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, tidak hanya melanggar martabat manusia, dalam beberapa situasi, hal itu merupakan ancaman terhadap hak untuk hidup.
Meskipun identifikasi makna kemiskinan membutuhkan kedalaman interdisipliner, bukan keluasan multidisipliner, banyak ilmuwan sosial telah menyoroti pendekatan yang berbeda untuk mendefinisikan kemiskinan.
Diskusi antara eksponen pendekatan yang berbeda tidak hanya bersaing tetapi juga menciptakan kebingungan yang lebih besar daripada kejelasan tidak hanya karena kurangnya kesepakatan tentang makna kata itu sendiri.
Masalah mendasarnya adalah bahwa penerimaan definisi spesifik sama saja dengan menerima garis kesepakatan tertentu.
Kemiskinan adalah penderitaan
Dengan mempertimbangkan semua kesulitan ini dalam mendefinisikan kemiskinan, seseorang dapat menganggap bahwa "kemiskinan adalah penderitaan”.
Biasanya orang miskin menderita kesakitan fisik akibat asupan makanan yang terlalu sedikit dengan kadar gizi rendah, ditambah dengan jam kerja yang panjang.
Selain penderitaan fisik, orang fisik mengalami penderitaan emosional yang berasal dari penghinaan sehari-hari akibat ketergantungan dan kurangnya kekuatan.
Mereka juga mengalami penderitaan moral karena dipaksa untuk membuat pilihan moral yang terkadang sangat dilematis. Misalnya, apakah mereka akan memakai ‘uang yang sedikit’ untuk menyelamatkan nyawa anggota keluarga yang sakit atau menggunakan uang tersebut untuk memberi makan anak-anak mereka?
Orang miskin juga berada pilihan sulit seperti ‘mempertahankan kemuliaan kejujuran/kebenaran’ atau membiarkan dirinya ‘diperalat’ oleh aktor intelektual sebagaimana sering terjadi dalam berbagai perkara lahan, termasuk kasus HGU Nangahale yang viral belakangan ini.
Bahkan, orang miskin juga berada pada pilihan sulit atas nilai susila’ seperti menyerahkan anak perempuannya direkrut oleh agen perdagangan manusia yang berkedok sebagai agen pekerja migran; menjajakan dirinya sendiri sebagai pekerja seks; ataukah mati kelaparan karena tak punya pendapatan?
Mirisnya lagi, setelah membuat pilihan sulit seperti itu mereka tetap saja miskin, bahkan semakin berada dalam ketergantungan kepada orang lain karena hak-hak mereka diremehkan bahkan diabaikan sama sekali.
Selain itu mereka juga masih menerima penghinaan atau di-bully oleh warga di sekitarnya.
Jadi, begitulah ‘beban beruntun’ yang senantiasa dipikul oleh ‘orang miskin’, salah seorang di antara lima orang NTT saat ini.
Apakah ada yang benar-benar peduli?
Sekali pun orang miskin (1,11 juta orang) itu adalah bagian integral dari masyarakat NTT, tetapi pemerintah dan masyarakat NTT tak terlalu peduli dengan ‘nasib’ mereka.
Betapa tidak? Dalam urusan adat-istiadat’ misalnya, orang miskin di NTT memiliki hak dan kewajiban yang sama persis dengan orang yang tidak miskin. Para pemangku adat sama sekali berpikir untuk memberikan ‘dispensasi adat’, untuk orang miskin. Contoh, menurunkan beban/kewajiban adat ‘babi besar’ dengan ‘ayam’.
Sementara itu, pihak lembaga agama seperti gereja -karena berbagai alasan- belum memiliki program kongkret yang benar-benar membuat orang miskin bisa secara permanen ‘terangkat’ keluar dari kemiskinan. Yang sering muncul justru adalah upaya advokasi ketika orang miskin berhadapan dengan masalah perdagangan manusia, kekerasan rumah tangga, penggusuran dan lain-lain.
Artinya, program yang disediakan lebih bersifat kuratif, bukan program untuk mengentaskan kemiskinan. Padahal, hampir semua masalah yang ditangani itu hampir pasti bersumber dari kemiskinan.
LSM pun juga demikian. Mereka lebih sibuk dengan urusan advokasi-advokasi, sangat sedikit LSM yang bergerak untuk melepaskan orang NTT keluar dari kemiskinan. Padahal, perputaran dana di kalangan LSM tak sedikit nilainya.
Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, termasuk pejabat di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan) tampak tak cukup peduli dengan orang miskin. Memang, dalam berbagai kesempatan, para pejabat berbicara mengenai program pengentasan kemiskinan.
Namun, dalam penerapannya program-program tersebut tidak dilakukan berdasarkan studi kelayakan dan desain/perencanaan serta pendampingan yang baik. Akibatnya, setelah sebuah program selesai dijalankan, kondisi warga miskin kembali seperti sedia kala.
Sebagai contoh kecil, di Desa Nata Ute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, pada akhir 2023 lalu, pemerintahan desa menggunakan dana desa, mengadakan program pembagian bibit ayam untuk warga miskin guna meningkatkan akses protein hewani dan kesejahteraan masyarakat (semestinya secara berkelanjutan).
Tanpa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), pemerintah desa tiba-tiba membagikan bantuan 10 bibit ayam kepada para ibu rumah tangga. Itu pun dikerjakan tanpa ada sosialisasi tentang cara berternak ayam, tanpa bantuan pakan, vitamin, obat-obatan, apalagi biaya pembuatan kandang.
Akibatnya, program itu tidak membawa perubahan apa pun. Bahkan, para ibu rumah tangga mengaku setelah 2- 3 bulan, tak ada lagi bibit ayam yang tersisa karena sudah dipotong untuk tamu ataupun dijual ke pasar.
Di banyak desa, karena tuntutan UU Desa, pemerintah desa berusaha taat hukum, mengadakan sebuah program melalui mekanisme Musrembangdes. Kemudia mereka berusaha menetapkan prosedur dan mekanisme pelaksanaan, pengawasan dan kemudian pelaporan.
Sekilas, tampak, semuanya berjalan sesuai prosedur yang telah digariskan. Namun, hasilnya, ‘sama we’e’, alias ‘sama saja’. Warga miskin, tetap saja hidup dalam kemiskinan sebagaimana sediakala.
Mengapa demikian? Pasalnya, program pengentasan kemiskinan memang diadakan untuk’ membuktikan kinerja’, yang kemudian diperlihatkan di data statistik.
Motivasi pengadaan program bukan untuk membawa orang miskin ‘keluar dari kondisi kemiskinannya’ secara tetap, tetapi untuk memperlihatkan kinerja, dan tentu saja ada tujuan politis (bisa terpilih lagi untuk masa jabatan kedua).
Yang juga tampak nyata adalah Pemda (Kabupaten/Kota dan Provinsi) berusaha mengentaskan kemiskinan dengan cara menjalankan program dari Pemerintah Pusat seperti BLT, bansos, KIP dll.
Sayangnya lagi, program tersebut dilakukan dengan komitmen yang rendah dan basis data yang lemah, sehingga tak jarang terjadi penyalurannya ‘simpang siur’. Warga penerima manfaat BLT misalnya bukan ‘orang miskin’ tetapi sebaliknya orang yang tidak miskin.
Di sektor pendidikan, Pemda di NTT juga menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Program ini bertujuan untuk antara lain: meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, mencegah siswa yang rentan putus sekolah, menarik kembali anak putus sekolah untuk bersekolah, dan meringankan biaya personal pendidikan.
Namun, penerapannya PIP juga tidak cukup efektif, sebagaimana sering diberitakan media ini. Pasalnya program ini pun dijalankan dengan motivasi politis.
Anggota DPR RI yang memfasilitasi PIP (dan juga KIP) biasanya dengan gagah berpidato memberi kesan seolah-olah dana beasiswa keluar dari dompet sendiri atau kas partainya.
Jadi, PIP pun tidak lagi menjadi alat untuk ’menyelamatkan orang miskin’ tetapi ‘alat invetasi politis’ supaya oknum dan partai politik tertentu dapat mendulang suara pada saat Pileg berikutnya.
Butuh waktu 55 tahun
Dalam konteks sebagaimana digambarkan di atas dapat dimaklumi betapa Pemda NTT merasa sangat berbunga-bunga ketika pada 15 Januari 2025 lalu, BPS merilis, penduduk miskin NTT per September 2024 tinggal 1,11 juta jiwa atau berkurang 19.630 jiwa dibandingkan dengan survei sebelumnya, Maret 2024.
Padahal, angka penurunannya hanya 0,46 persen. Bisa dibayangkan, jika jumlah penurunannya konsisten demikian, maka NTT perlu sekitar 55 tahun untuk mengentaskan seluruh orang miskin yang berjumlah 1,11 juta itu.
Makanya, sangat tepat ketika membuat laporan mengenai rilis BPS tersebut, Kompas.id menulis judul yang bernada sarkasme: “Penduduk Miskin NTT Berkurang, Yang Benar Saja...”. ****